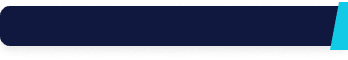Budayawan dan Sejarawan Banyuwangi Tak Sudi Dipecah Belah

Budayawan dan Sejarawan Banyuwangi Tak Sudi Dipecah Belah
A
A
A
BANYUWANGI - Setajam apapun kritik, jika konstruktif, proporsional, akan menjadi vitamin buat perbaikan dan kemajuan. Setumpul apapun kritik, jika bermuatan SARA dan fitnah, hanya akan menciptakan luka-luka baru. Apalagi hanya untuk kepentingan jangka pendek.
Beruntung, orang Banyuwangi, tiyang Blambangan, masyarakat Osing, tidak mudah diprovokasi, diadu-adu, sekalipun dengan isu SARA. Termasuk catatan opini yang berkeliaran, disebarluaskan melalui whatsapps group, soal fitnah “arabisasi” dalam pengembangan pariwisata halal di Banyuwangi.
Aekanu, dosen, budayawan dan pengamat dan pemerhati sejarah Banyuwangi menjelaskan, Pulau Santen yang dipromosikan sebagai pantai destinasi halal, sejatinya hanya semata-mata agar menarik wisatawan lebih banyak.
“Juga agar bersih, tertata rapi, menarik buat dikunjungi dan akhirnya menghasilkan aktivitas ekonomi buat masyarakat. Awalnya pantai ini kumuh dan kotor,” jelas Aekanu.
Menurut Aekanu, ini bukan strategi untuk meng"Arab"kan atau Arabisasi. Terlalu jauh dan mengada-ada, menggunakan analisa peng-Arab-an di Pantai Santen.
“Bahkan menuju ke pantai Santen ini, pengunjung melewati kawasan Pecinan, ada Klenteng untuk penganut Konghuchou yang notabene kumpulan agama Budha dan Konghucu. Selama ini oke-oke saja. Jadi, jangan coba-coba memancing isu SARA di Banyuwangi,” tegas Aekanu.
Dia juga menjelaskan, menuju ke destinasi ini juga melintasi makam atau tempat ngaben umat Hindu. “Dan, semua nyaman saja, saling menghormati, saling bertoleransi. Banyuwangi itu masyarakatnya paham akan spirit toleransi,” ungkap Aekanuz
Dia juga memaparkan bahwa sistem budaya, tradisi lokal, upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Osing masih utuh. Mereka diberi ruang apresiasi dan didukung oleh pemerintah daerah. “Di sini tidak ada tanda tanda sedikitpun yang mengarah pada intervensi pemerintah untuk meng"Arab" kan Osing. Bahkan, berbagai festival budaya masyarakat Osing digelar tiap tahun, jumlahnya puluhan,” kata Aekanu.
“Di Alun-Alun Blambangan bahkan dilarang ada pementasan kecuali pentas seni-budaya masyarakat yang sebagian besar penampilannya adalah khas Suku Osing,” imbuh Aekanu.
Dia mengamati, bahwa semua bentuk upacara Hindu dan pura yang dibangun, pemerintah mendukung dan tidak ada yang menghambat apalagi melarang. “Ini bukti nyata bahwa pemerintah tidak meng"Arab"kan penganut Hindu,” tandasnya.
“Terlalu “kasar” jika memelintir sesuatu yang menyentuh agama. Terlalu ngawur berspekulasi dengan isu agama di Banyuwangi,” tegasnya lagi.
Penulis buku tentang berbagai hal terkait Suku Osing dan sekaligus budayawan, Antariksawan Yusuf juga mengecam keras permainan isu SARA yang mencoba membenturkan umat Hindu dan Islam di Banyuwangi. Antariksawan, putra asli Banyuwangi, tidak ingin daerahnya diacak-acak oleh pemahaman yang salah kaprah untuk kepentingan sesaat.
“Agama itu untuk manusia. Tanah, batu, udara, air, api, itu tidak beragama. Sebelum Hindu datang, diperkirakan para era Rshi Markandya abad 6-7, di Banyuwangi ini sudah ada peradaban megalitikum yang tecermin dalam Situs Kandanglembu dengan kepercayaan Animisme Dinamisme,” tegas Antariksawan Yusuf.
Dari situ, lanjut Antariksawan, apakah bisa ditarik kesimpulan bahwa Hindu telah meng-India-kan Banyuwangi dan menyingkirkan kepercayaan masyarakat asli yang sudah ada sebelumnya. “Tentu tidak begitu! Maka menggunakan diksi Arabisasi itu terlalu memaksakan sejarah dengan tafsiran yang pendek!” tegasnya.
Dia menegaskan, bahwa ujung dari semua konflik di tanah air di zaman Belanda adalah politik devide et impera. Memecah belah untuk menguasai. Hanya dengan memecah belah, Belanda bisa menguasai. “Jangan lagi menggunakan politik itu, untuk Banyuwangi yang sudah makin maju dan damai,” ujar Antariksawan.
Terlalu mahal, membangun kedamaian, menciptakan optimisme, membuat situasi kondusif untuk bergerak maju. Apalagi, di sektor pariwisata, yang membutuhkan ekosistem damai, tenteram, dan penuh keramahan.
Masyarakat Banyuwangi sudah membuktikan bahwa pariwisatalah yang menyulap daerahnya menjadi hebat dan berprestasi, sehingga puluhan kabupaten kota di Indonesia belajar dari sukses Banyuwangi.
Kembali ke soal sejarah, Antariksawan melanjutkan, Belanda di mana-mana menggunakan siasat pecah belah. Dengan mempertentangkan antar suku, antar kerajaan, antar putera pangeran, antar keluarga kerajaan, antar agama, antar aliran, antar kekuatan.
“Apakah kita akan kembali ke era konflik antar saudara sendiri? Tentu kita tidak mau, dan jangan dipancing dengan logika yang salah,” tegasnya.
Sekali lagi, lanjut Antariksawan, konflik dalam sejarah Blambangan alias Banyuwangi di masa lampau tidak sepenuhnya berhulu di unsur agama dan suku, melainkan unsur politik. Tujuannya menguasai! “Perebutan kekuasaan antar keluarga yang menjadi sebab keretakan persatuan dan menjadi pintu masuk Belanda,” tuturnya.
“Secepat apapun kebohongan berlari, yakinlah kebenaran akan melewatinya. Sehebat apapun membungkus analisa, jika untuk menghancurkan kekerabatan tradisi budaya, pasti akan kelihatan belangnya. Jangan memecah kerukunan umat di Banyuwangi!” pungkas Antariksawan.
Beruntung, orang Banyuwangi, tiyang Blambangan, masyarakat Osing, tidak mudah diprovokasi, diadu-adu, sekalipun dengan isu SARA. Termasuk catatan opini yang berkeliaran, disebarluaskan melalui whatsapps group, soal fitnah “arabisasi” dalam pengembangan pariwisata halal di Banyuwangi.
Aekanu, dosen, budayawan dan pengamat dan pemerhati sejarah Banyuwangi menjelaskan, Pulau Santen yang dipromosikan sebagai pantai destinasi halal, sejatinya hanya semata-mata agar menarik wisatawan lebih banyak.
“Juga agar bersih, tertata rapi, menarik buat dikunjungi dan akhirnya menghasilkan aktivitas ekonomi buat masyarakat. Awalnya pantai ini kumuh dan kotor,” jelas Aekanu.
Menurut Aekanu, ini bukan strategi untuk meng"Arab"kan atau Arabisasi. Terlalu jauh dan mengada-ada, menggunakan analisa peng-Arab-an di Pantai Santen.
“Bahkan menuju ke pantai Santen ini, pengunjung melewati kawasan Pecinan, ada Klenteng untuk penganut Konghuchou yang notabene kumpulan agama Budha dan Konghucu. Selama ini oke-oke saja. Jadi, jangan coba-coba memancing isu SARA di Banyuwangi,” tegas Aekanu.
Dia juga menjelaskan, menuju ke destinasi ini juga melintasi makam atau tempat ngaben umat Hindu. “Dan, semua nyaman saja, saling menghormati, saling bertoleransi. Banyuwangi itu masyarakatnya paham akan spirit toleransi,” ungkap Aekanuz
Dia juga memaparkan bahwa sistem budaya, tradisi lokal, upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Osing masih utuh. Mereka diberi ruang apresiasi dan didukung oleh pemerintah daerah. “Di sini tidak ada tanda tanda sedikitpun yang mengarah pada intervensi pemerintah untuk meng"Arab" kan Osing. Bahkan, berbagai festival budaya masyarakat Osing digelar tiap tahun, jumlahnya puluhan,” kata Aekanu.
“Di Alun-Alun Blambangan bahkan dilarang ada pementasan kecuali pentas seni-budaya masyarakat yang sebagian besar penampilannya adalah khas Suku Osing,” imbuh Aekanu.
Dia mengamati, bahwa semua bentuk upacara Hindu dan pura yang dibangun, pemerintah mendukung dan tidak ada yang menghambat apalagi melarang. “Ini bukti nyata bahwa pemerintah tidak meng"Arab"kan penganut Hindu,” tandasnya.
“Terlalu “kasar” jika memelintir sesuatu yang menyentuh agama. Terlalu ngawur berspekulasi dengan isu agama di Banyuwangi,” tegasnya lagi.
Penulis buku tentang berbagai hal terkait Suku Osing dan sekaligus budayawan, Antariksawan Yusuf juga mengecam keras permainan isu SARA yang mencoba membenturkan umat Hindu dan Islam di Banyuwangi. Antariksawan, putra asli Banyuwangi, tidak ingin daerahnya diacak-acak oleh pemahaman yang salah kaprah untuk kepentingan sesaat.
“Agama itu untuk manusia. Tanah, batu, udara, air, api, itu tidak beragama. Sebelum Hindu datang, diperkirakan para era Rshi Markandya abad 6-7, di Banyuwangi ini sudah ada peradaban megalitikum yang tecermin dalam Situs Kandanglembu dengan kepercayaan Animisme Dinamisme,” tegas Antariksawan Yusuf.
Dari situ, lanjut Antariksawan, apakah bisa ditarik kesimpulan bahwa Hindu telah meng-India-kan Banyuwangi dan menyingkirkan kepercayaan masyarakat asli yang sudah ada sebelumnya. “Tentu tidak begitu! Maka menggunakan diksi Arabisasi itu terlalu memaksakan sejarah dengan tafsiran yang pendek!” tegasnya.
Dia menegaskan, bahwa ujung dari semua konflik di tanah air di zaman Belanda adalah politik devide et impera. Memecah belah untuk menguasai. Hanya dengan memecah belah, Belanda bisa menguasai. “Jangan lagi menggunakan politik itu, untuk Banyuwangi yang sudah makin maju dan damai,” ujar Antariksawan.
Terlalu mahal, membangun kedamaian, menciptakan optimisme, membuat situasi kondusif untuk bergerak maju. Apalagi, di sektor pariwisata, yang membutuhkan ekosistem damai, tenteram, dan penuh keramahan.
Masyarakat Banyuwangi sudah membuktikan bahwa pariwisatalah yang menyulap daerahnya menjadi hebat dan berprestasi, sehingga puluhan kabupaten kota di Indonesia belajar dari sukses Banyuwangi.
Kembali ke soal sejarah, Antariksawan melanjutkan, Belanda di mana-mana menggunakan siasat pecah belah. Dengan mempertentangkan antar suku, antar kerajaan, antar putera pangeran, antar keluarga kerajaan, antar agama, antar aliran, antar kekuatan.
“Apakah kita akan kembali ke era konflik antar saudara sendiri? Tentu kita tidak mau, dan jangan dipancing dengan logika yang salah,” tegasnya.
Sekali lagi, lanjut Antariksawan, konflik dalam sejarah Blambangan alias Banyuwangi di masa lampau tidak sepenuhnya berhulu di unsur agama dan suku, melainkan unsur politik. Tujuannya menguasai! “Perebutan kekuasaan antar keluarga yang menjadi sebab keretakan persatuan dan menjadi pintu masuk Belanda,” tuturnya.
“Secepat apapun kebohongan berlari, yakinlah kebenaran akan melewatinya. Sehebat apapun membungkus analisa, jika untuk menghancurkan kekerabatan tradisi budaya, pasti akan kelihatan belangnya. Jangan memecah kerukunan umat di Banyuwangi!” pungkas Antariksawan.
(akn)