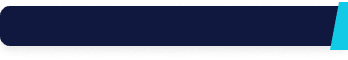Menghidupkan Kembali Lafran Pane

Menghidupkan Kembali Lafran Pane
A
A
A
Sosoknya dikenal luas oleh para kader dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di seluruh Indonesia, bahkan yang berada di mancanegara. Meski demikian, jejak pemikiran, sikap, tindakan, dan keteladanannya melampaui batas organisasi HMI.
Sepertinya memang dia terlahir bukan semata untuk HMI, melainkan untuk Indonesia dan Islam serta untuk umat, bangsa, dan negara. Boleh dibilang ketokohannya melampaui masanya dan tempat di mana dia terlahir, tumbuh, dan hidup. Dalam diri dan perjalanan hidupnya terdapat ibrah yang sangat relevan bagi kita semua termasuk generasi milenial saat ini, yakni merdeka sejak hati, Islam sejak nurani, dan Indonesia sejak ragawi.
Maka tidak berlebihan-bahkan mungkin memang menjadi sebuah keharusan-pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional untuknya pada 6 November 2017. Lafran Pane, anak dari pasangan Sutan Pangurabaan dan Gonto Siregar.
Lafran terlahir di Sipirok, Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada 5 Februari 1922, dan meninggal di Yogyakarta pada 25 Januari 1991. Ayah Lafran merupakan guru, wartawan, dan sastrawan sekaligus salah satu tokoh Muhammadiyah di Sipriok, bahkan pendiri sekolah dan pesantren Muhammadiyah pertama di Sipirok.
Sosok Lafran Pane diulas secara lugas, mengalir, jernih, utuh, dan gamblang oleh Ahmad Fuadi dalam novel berjudul Merdeka Sejak Hati. Membaca novel ini ibaratnya kita sedang jumpa muka, pikiran, dan jiwa dengan Lafran. Fuadi membagi jalan cerita dengan 41 pembabakan. Tapi, jika dirangkum, boleh disebut ada enam lokasi kunci pembabakan, yakni Sipirok, Medan, Batavia (Jakarta), Yogyakarta, Malang, dan Bengkulu.
Lintasan kehidupan Lafran yang dimulai sejak kecil dalam keluarga terpatri dengan lima hal, yakni buku, pergerakan untuk kemerdekaan, Islam, empati terhadap sesama, dan pendidikan. Lintasan kehidupannya juga dipenuhi dan disertai berbagai sosok orang pergerakan di tanah kelahirannya, anak jalanan, preman, pedagang di pasar dan jalanan, sarung dan ring tinju, geng motor, ulama-guru, bahkan tokoh-tokoh penting mulai dari DN Aidit, Soekarno (Bung Karno), Mohammad Hatta (Bung Hatta), dan Sutan Syahrir, termasuk tentu saja dua kakak kandung Lafran, Sanusi Pane dan Armijn Pane.
Juga diceritakan bagaimana Lafran bersinggungan dengan para tokoh pendidikan di Yogyakarta seperti KH Abdul Kahar Muzakkir, Husein Yahya, dan HM Rasyidi, para mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI) Yogyakarta dan lintas kampus, para pendiri (ashabul awwalun ) HMI, tokoh-tokoh organisasi kemahasiswaan dan pelajar, tokoh-tokoh organisasi Islam dan nasionalis, tentara dan tokoh tentara terutama Panglima Besar Jenderal Sudirman, para intelektual, dan masih banyak lagi.
Membaca novel Merdeka Sejak Hati seolah kita berada di samping Lafran Pane atau boleh dibilang kita adalah bayangannya di mana saja Lafran ada dan ke mana saja pergi. Ahmad Fuadi mampu menyatukan kepingan-kepingan perjalanan hidup dan sikap; perjuangan sebelum, saat, dan sesudah proklamasi kemerdekaan; dan kecintaan Lafran terhadap rakyat (umat), bangsa, negara, dan agama (Islam) sehingga mengha dirkan goresan sejarah dengan gaya yang unik, apik, mudah dicerna, dan bisa dijadikan contoh oleh para pembaca.
Fuadi berhasil menghadirkan Lafran dan jalan hidupnya yang berliku, penuh tantangan, onak dan duri, jatuh dan bangkit kembali, kemudian berjuang memerdekakan pikiran dan jiwa rakyat Indonesia serta meninggikan agama Allah.
Membacanya membuat bercampur aduk segala rasa dan perasaan. Salut untuk Fuadi yang mampu mengorkestrai kata demi kata, frasa demi frasa, kalimat demi kalimat, maupun paragraf demi paragraf. Fuadi berhasil “menghidupkan kembali” Lafran Pane. Fuadi juga mampu menghadirkan Lafran sebagai pencinta kopi yang menguasai enam bahasa asing: Belanda, China, Prancis, Jerman, Jepang, dan Inggris serta pengajar, pendidik, dan intelektual yang mencintai pendidikan dan ilmu pengetahuan sekaligus penyayang keluarga.
Novel Merdeka Sejak Hati sangat jelas menghimpun Lafran dalam satu tarikan nafas dengan tiga kata saja, yaitu beriman, berilmu, dan beramal. Atau, dengan empat kata lain, yakni kemodernan, keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan yang cocok, berkesesuaian, seirama, dan sejalan. Dari novel ini kita pun bisa mengetahui betapa Lafran-si anak piatu-memiliki pemikiran dan tindakan dalam berbagai aspek yang hingga kini masih dan sangat relevan.
Mulai dari karakter seorang pejuang dan petarung dalam menjalani kehidupan. Bicara tentang nilai antikorupsi Lafran, Fuadi bahkan langsung menghadirkannya di awal babak. Nilai tersebut tertuang dalam pernyataan Lafran kepada anaknya, Muhammad Iqbal Pane.
“Bagiku, kedudukan itu untuk diamanahkan kepada yang lebih mampu, bukan diperebutkan bagai piala. Agar ada kemajuan, ada progres, agar harkat martabat bangsa ini naik, agar hilang kolusi dan korupsi. Kekuasaan bukan alat untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk memperkaya bangsa. Inilah yang menurutku kebiasaan yang benar.
Bukan membenarkan yang biasa.” Tak ada gading yang tak retak. Menurut saya, ada dua catatan kecil untuk novel ini. Pertama , wajah sosok bersepeda di cover novel sepintas bukan seperti Lafran Pane. Tetapi, dari sisi semiotika komunikasi, cover novel ini mampu memperhalus kehadiran HMI dengan tiga warna hijau, hitam, dan putih atau boleh dibilang dua warna saja, hijau dan hitam, menunjukkan Indonesia (keindonesiaan) lewat warna merah dan putih, dan menghadirkan nuansa kesederhanaan Lafran dengan sepeda ontelnya.
Kedua , novel ini tidak terlalu mengeksplor tentang persentuhan dan perdebatan pemikiran secara mendalam antara Lafran dengan DN Aidit yang sama-sama teman satu kelas di Taman Siswa (Taman Dewasa Raya Batavia) dan teman satu organisasi di Gerakan Rakyat Indonesia. Selain itu, persentuhan Lafran dengan Bung Karno, Bung Hatta, dan Sutan Syahrir disinggung sekadar saja.
Dari sudut pandang berbeda, bagi saya, novel karya Ahmad Fuadi ini berpadu sempurna dengan buku biografi berjudul Lafran Pane: Jejak dan Pemikirannya (2010) karya Hariqo Wibawa Satria. Fuadi dan Hariqo, dua alumni Pondok Modern Gontor, Ponorogo, patut mendapat kredit dan apresiasi lebih atas upaya mereka menghadirkan sosok Lafran Pane.
Apalagi, karya keduanya berbasis pada riset yang utuh, menyeluruh, dan mendalam. Sekali lagi, kehadiran novel Merdeka Sejak Hati kembali menegaskan bahwa Lafran Pane bukan semata milik HMI, tapi milik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Begitu pun HMI. HMI bukan semata milik HMI, kader, dan alumninya, tapi milik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia.
Karenanya, novel ini layak dibaca oleh siapa pun, apa pun latar belakang sosial, keagamaan, dan pekerjaan, maupun kalangan anak-anak, remaja, pemuda, hingga orang tua. Bagaimanapun, Lafran Pane dan keteladanannya layak tetap hidup dalam hati, pikiran, dan jiwa putra-putri Bumi Pertiwi Indonesia dan umat Islam di Indonesia.
Sebagaimana Hadits: “Jika keturunan Adam (seorang manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, atau ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan, atau doa anak yang saleh.”Hadits Riwayat Muslim. Ya, si Beliung yang kemudian menjadi guru besar ilmu tata negara itu telah meninggalkan tiga perkara itu, terutama amal jariah.
Sabir laluhu
jurnalis, penulis, dan alumnus HMI Cabang Ciputat
Sepertinya memang dia terlahir bukan semata untuk HMI, melainkan untuk Indonesia dan Islam serta untuk umat, bangsa, dan negara. Boleh dibilang ketokohannya melampaui masanya dan tempat di mana dia terlahir, tumbuh, dan hidup. Dalam diri dan perjalanan hidupnya terdapat ibrah yang sangat relevan bagi kita semua termasuk generasi milenial saat ini, yakni merdeka sejak hati, Islam sejak nurani, dan Indonesia sejak ragawi.
Maka tidak berlebihan-bahkan mungkin memang menjadi sebuah keharusan-pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional untuknya pada 6 November 2017. Lafran Pane, anak dari pasangan Sutan Pangurabaan dan Gonto Siregar.
Lafran terlahir di Sipirok, Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada 5 Februari 1922, dan meninggal di Yogyakarta pada 25 Januari 1991. Ayah Lafran merupakan guru, wartawan, dan sastrawan sekaligus salah satu tokoh Muhammadiyah di Sipriok, bahkan pendiri sekolah dan pesantren Muhammadiyah pertama di Sipirok.
Sosok Lafran Pane diulas secara lugas, mengalir, jernih, utuh, dan gamblang oleh Ahmad Fuadi dalam novel berjudul Merdeka Sejak Hati. Membaca novel ini ibaratnya kita sedang jumpa muka, pikiran, dan jiwa dengan Lafran. Fuadi membagi jalan cerita dengan 41 pembabakan. Tapi, jika dirangkum, boleh disebut ada enam lokasi kunci pembabakan, yakni Sipirok, Medan, Batavia (Jakarta), Yogyakarta, Malang, dan Bengkulu.
Lintasan kehidupan Lafran yang dimulai sejak kecil dalam keluarga terpatri dengan lima hal, yakni buku, pergerakan untuk kemerdekaan, Islam, empati terhadap sesama, dan pendidikan. Lintasan kehidupannya juga dipenuhi dan disertai berbagai sosok orang pergerakan di tanah kelahirannya, anak jalanan, preman, pedagang di pasar dan jalanan, sarung dan ring tinju, geng motor, ulama-guru, bahkan tokoh-tokoh penting mulai dari DN Aidit, Soekarno (Bung Karno), Mohammad Hatta (Bung Hatta), dan Sutan Syahrir, termasuk tentu saja dua kakak kandung Lafran, Sanusi Pane dan Armijn Pane.
Juga diceritakan bagaimana Lafran bersinggungan dengan para tokoh pendidikan di Yogyakarta seperti KH Abdul Kahar Muzakkir, Husein Yahya, dan HM Rasyidi, para mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI) Yogyakarta dan lintas kampus, para pendiri (ashabul awwalun ) HMI, tokoh-tokoh organisasi kemahasiswaan dan pelajar, tokoh-tokoh organisasi Islam dan nasionalis, tentara dan tokoh tentara terutama Panglima Besar Jenderal Sudirman, para intelektual, dan masih banyak lagi.
Membaca novel Merdeka Sejak Hati seolah kita berada di samping Lafran Pane atau boleh dibilang kita adalah bayangannya di mana saja Lafran ada dan ke mana saja pergi. Ahmad Fuadi mampu menyatukan kepingan-kepingan perjalanan hidup dan sikap; perjuangan sebelum, saat, dan sesudah proklamasi kemerdekaan; dan kecintaan Lafran terhadap rakyat (umat), bangsa, negara, dan agama (Islam) sehingga mengha dirkan goresan sejarah dengan gaya yang unik, apik, mudah dicerna, dan bisa dijadikan contoh oleh para pembaca.
Fuadi berhasil menghadirkan Lafran dan jalan hidupnya yang berliku, penuh tantangan, onak dan duri, jatuh dan bangkit kembali, kemudian berjuang memerdekakan pikiran dan jiwa rakyat Indonesia serta meninggikan agama Allah.
Membacanya membuat bercampur aduk segala rasa dan perasaan. Salut untuk Fuadi yang mampu mengorkestrai kata demi kata, frasa demi frasa, kalimat demi kalimat, maupun paragraf demi paragraf. Fuadi berhasil “menghidupkan kembali” Lafran Pane. Fuadi juga mampu menghadirkan Lafran sebagai pencinta kopi yang menguasai enam bahasa asing: Belanda, China, Prancis, Jerman, Jepang, dan Inggris serta pengajar, pendidik, dan intelektual yang mencintai pendidikan dan ilmu pengetahuan sekaligus penyayang keluarga.
Novel Merdeka Sejak Hati sangat jelas menghimpun Lafran dalam satu tarikan nafas dengan tiga kata saja, yaitu beriman, berilmu, dan beramal. Atau, dengan empat kata lain, yakni kemodernan, keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan yang cocok, berkesesuaian, seirama, dan sejalan. Dari novel ini kita pun bisa mengetahui betapa Lafran-si anak piatu-memiliki pemikiran dan tindakan dalam berbagai aspek yang hingga kini masih dan sangat relevan.
Mulai dari karakter seorang pejuang dan petarung dalam menjalani kehidupan. Bicara tentang nilai antikorupsi Lafran, Fuadi bahkan langsung menghadirkannya di awal babak. Nilai tersebut tertuang dalam pernyataan Lafran kepada anaknya, Muhammad Iqbal Pane.
“Bagiku, kedudukan itu untuk diamanahkan kepada yang lebih mampu, bukan diperebutkan bagai piala. Agar ada kemajuan, ada progres, agar harkat martabat bangsa ini naik, agar hilang kolusi dan korupsi. Kekuasaan bukan alat untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk memperkaya bangsa. Inilah yang menurutku kebiasaan yang benar.
Bukan membenarkan yang biasa.” Tak ada gading yang tak retak. Menurut saya, ada dua catatan kecil untuk novel ini. Pertama , wajah sosok bersepeda di cover novel sepintas bukan seperti Lafran Pane. Tetapi, dari sisi semiotika komunikasi, cover novel ini mampu memperhalus kehadiran HMI dengan tiga warna hijau, hitam, dan putih atau boleh dibilang dua warna saja, hijau dan hitam, menunjukkan Indonesia (keindonesiaan) lewat warna merah dan putih, dan menghadirkan nuansa kesederhanaan Lafran dengan sepeda ontelnya.
Kedua , novel ini tidak terlalu mengeksplor tentang persentuhan dan perdebatan pemikiran secara mendalam antara Lafran dengan DN Aidit yang sama-sama teman satu kelas di Taman Siswa (Taman Dewasa Raya Batavia) dan teman satu organisasi di Gerakan Rakyat Indonesia. Selain itu, persentuhan Lafran dengan Bung Karno, Bung Hatta, dan Sutan Syahrir disinggung sekadar saja.
Dari sudut pandang berbeda, bagi saya, novel karya Ahmad Fuadi ini berpadu sempurna dengan buku biografi berjudul Lafran Pane: Jejak dan Pemikirannya (2010) karya Hariqo Wibawa Satria. Fuadi dan Hariqo, dua alumni Pondok Modern Gontor, Ponorogo, patut mendapat kredit dan apresiasi lebih atas upaya mereka menghadirkan sosok Lafran Pane.
Apalagi, karya keduanya berbasis pada riset yang utuh, menyeluruh, dan mendalam. Sekali lagi, kehadiran novel Merdeka Sejak Hati kembali menegaskan bahwa Lafran Pane bukan semata milik HMI, tapi milik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Begitu pun HMI. HMI bukan semata milik HMI, kader, dan alumninya, tapi milik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia.
Karenanya, novel ini layak dibaca oleh siapa pun, apa pun latar belakang sosial, keagamaan, dan pekerjaan, maupun kalangan anak-anak, remaja, pemuda, hingga orang tua. Bagaimanapun, Lafran Pane dan keteladanannya layak tetap hidup dalam hati, pikiran, dan jiwa putra-putri Bumi Pertiwi Indonesia dan umat Islam di Indonesia.
Sebagaimana Hadits: “Jika keturunan Adam (seorang manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, atau ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan, atau doa anak yang saleh.”Hadits Riwayat Muslim. Ya, si Beliung yang kemudian menjadi guru besar ilmu tata negara itu telah meninggalkan tiga perkara itu, terutama amal jariah.
Sabir laluhu
jurnalis, penulis, dan alumnus HMI Cabang Ciputat
(don)