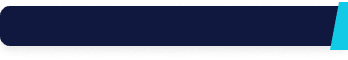Monster di Medan Perang

Monster di Medan Perang
A
A
A
Melanjutkan film pertama Monsters (2010), Dark Continent mencoba membuat premis yang lebih membuat penasaran. Para tentara tak hanya berhadapan dengan para monster, juga gerombolan pemberontak di Timur Tengah.
Jika di film pertama tokoh utamanya adalah seorang jurnalis foto, kini sutradara Tom Green yang menggantikan posisi Gareth Edwards menempatkan seorang pemuda pengangguran asal Detroit, Michael (Sam Keeley) sebagai tokoh sentralnya. Di awal, kita sudah diberi gambaran tentang Michael, juga apa yang terjadi setelah peristiwa di Monsters berlalu.
10 tahun sejak kejadian Monsters, makhluk asing bertentakel raksasa tersebut tetap menjadi ancaman bagi penduduk bumi. Bahkan, kehadirannya sudah sampai menginvasi wilayah Timur Tengah. Tentara Amerika cukup kewalahan mengatasinya. Apalagi dengan tambahan mengurusi kaum pemberontak di wilayah tersebut.
Saat Angkatan Darat Amerika membuka lowongan pendaftaran tentara, Michael melamar. Keinginannya menjadi tentara sebenarnya bukan urusan nasionalisme, tapi lebih pada sebuah pelarian. Dia ingin keluar dari Detroit yang dianggapnya tak memberi harapan. Tak punya satu pun sanak saudara, hatinya semakin mantap pergi ke Timur Tengah.
Apalagi sahabat yang dianggapnya sebagai saudara, Frankie (Joe Dempsie), juga ikut bersamanya. Di medan perang, Michael dan Frankie serta dua teman mereka, Williams (Parker Sawyers) dan Conway (Jesse Nagy), berada dalam tim pimpinan Frater (Johnny Harris). Dalam misi mengalahkan perang dan menghancurkan monster inilah, kepiluan perang harus mereka alami.
Saat pertama kali membuka kisahnya, Tom Green seolah-olah memberi sinyal kepada penonton bahwa dia ingin membuat film ini sebagai film laga perang yang penuh nuansa drama dan ikatan emosional antara para tokoh utamanya. Namun yang terjadi adalah, Green dan penulis skenario Jay Basu tampak tersesat di tengah jalan. Tak ada satu pun elemen, baik elemen film laga maupun drama perang, yang tergarap dengan baik.
Kehadiran monster meski sering terlihat dan berbentuk masif tidak mampu memberikan efek kejut dan ketegangan yang umumnya ada di filmfilm seperti Godzilla atau Jurassic Park. Tak ada ancaman berarti yang para monster ini berikan kepada para tentara kecuali hanya berkeliaran tak tentu arah dan menghancurkan tebing atau karang.
Sama halnya dengan kehadiran para pemberontak yang tak jelas asal-usul atau nama organisasinya. Seolah-olah mereka hadir dalam film ini hanya agar Frater dan pasukannya bisa melepas peluru dari senjata mereka. Begitu pula dengan elemen dramanya. Prolog awal tentang kehidupan Michael dan hubungannya dengan kawan-kawan setimnya, juga soal reputasi Frater, seolah hilang tak berbekas seiring cerita berjalan.
Hubungan emosional yang ingin ditunjukkan sutradara gagal tersampaikan, hingga akhirnya hanya berakhir sebagai sebuah klise. Belum lagi kerapuhan emosi para tentara, yang malah terlihat sebagai sebuah kecengengan belaka. Bayangkan, Frater yang menjadi pemimpin tim, sudah menjadi tentara selama 12 tahun dan berada di medan perang selama 8 tahun, bagaimana mungkin digambarkan memiliki emosi seperti Michael yang masih anak bawang di medan perang.
Kalaupun Frater tertekan secara psikologis akibat kerinduannya pada keluarga, tetap saja terasa tak logis, terutama karena tekanan psikologis yang dialami Frater tak sanggup diberi gambaran yang mendalam oleh sutradara dan penulis film ini.
Dark Continent malah sibuk dengan urusan memilih musik yang tepat untuk adegan-adegan perang, atau adeganadegan yang seharusnya mengharukan. Sungguh disayangkan mengingat premis film ini, juga posternya sudah sedemikian membuat penasaran.
Herita endriana
Jika di film pertama tokoh utamanya adalah seorang jurnalis foto, kini sutradara Tom Green yang menggantikan posisi Gareth Edwards menempatkan seorang pemuda pengangguran asal Detroit, Michael (Sam Keeley) sebagai tokoh sentralnya. Di awal, kita sudah diberi gambaran tentang Michael, juga apa yang terjadi setelah peristiwa di Monsters berlalu.
10 tahun sejak kejadian Monsters, makhluk asing bertentakel raksasa tersebut tetap menjadi ancaman bagi penduduk bumi. Bahkan, kehadirannya sudah sampai menginvasi wilayah Timur Tengah. Tentara Amerika cukup kewalahan mengatasinya. Apalagi dengan tambahan mengurusi kaum pemberontak di wilayah tersebut.
Saat Angkatan Darat Amerika membuka lowongan pendaftaran tentara, Michael melamar. Keinginannya menjadi tentara sebenarnya bukan urusan nasionalisme, tapi lebih pada sebuah pelarian. Dia ingin keluar dari Detroit yang dianggapnya tak memberi harapan. Tak punya satu pun sanak saudara, hatinya semakin mantap pergi ke Timur Tengah.
Apalagi sahabat yang dianggapnya sebagai saudara, Frankie (Joe Dempsie), juga ikut bersamanya. Di medan perang, Michael dan Frankie serta dua teman mereka, Williams (Parker Sawyers) dan Conway (Jesse Nagy), berada dalam tim pimpinan Frater (Johnny Harris). Dalam misi mengalahkan perang dan menghancurkan monster inilah, kepiluan perang harus mereka alami.
Saat pertama kali membuka kisahnya, Tom Green seolah-olah memberi sinyal kepada penonton bahwa dia ingin membuat film ini sebagai film laga perang yang penuh nuansa drama dan ikatan emosional antara para tokoh utamanya. Namun yang terjadi adalah, Green dan penulis skenario Jay Basu tampak tersesat di tengah jalan. Tak ada satu pun elemen, baik elemen film laga maupun drama perang, yang tergarap dengan baik.
Kehadiran monster meski sering terlihat dan berbentuk masif tidak mampu memberikan efek kejut dan ketegangan yang umumnya ada di filmfilm seperti Godzilla atau Jurassic Park. Tak ada ancaman berarti yang para monster ini berikan kepada para tentara kecuali hanya berkeliaran tak tentu arah dan menghancurkan tebing atau karang.
Sama halnya dengan kehadiran para pemberontak yang tak jelas asal-usul atau nama organisasinya. Seolah-olah mereka hadir dalam film ini hanya agar Frater dan pasukannya bisa melepas peluru dari senjata mereka. Begitu pula dengan elemen dramanya. Prolog awal tentang kehidupan Michael dan hubungannya dengan kawan-kawan setimnya, juga soal reputasi Frater, seolah hilang tak berbekas seiring cerita berjalan.
Hubungan emosional yang ingin ditunjukkan sutradara gagal tersampaikan, hingga akhirnya hanya berakhir sebagai sebuah klise. Belum lagi kerapuhan emosi para tentara, yang malah terlihat sebagai sebuah kecengengan belaka. Bayangkan, Frater yang menjadi pemimpin tim, sudah menjadi tentara selama 12 tahun dan berada di medan perang selama 8 tahun, bagaimana mungkin digambarkan memiliki emosi seperti Michael yang masih anak bawang di medan perang.
Kalaupun Frater tertekan secara psikologis akibat kerinduannya pada keluarga, tetap saja terasa tak logis, terutama karena tekanan psikologis yang dialami Frater tak sanggup diberi gambaran yang mendalam oleh sutradara dan penulis film ini.
Dark Continent malah sibuk dengan urusan memilih musik yang tepat untuk adegan-adegan perang, atau adeganadegan yang seharusnya mengharukan. Sungguh disayangkan mengingat premis film ini, juga posternya sudah sedemikian membuat penasaran.
Herita endriana
(bbg)