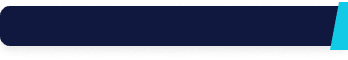Realisme Magis Genevieve Couteau

Realisme Magis Genevieve Couteau
A
A
A
GENEVIEVE Couteau mungkin tidak seakrab nama para perupa yang berkontribusi terhadap kemajuan seni rupa di Bali, seperti Walter Spies, Rudolf Bonnet, Le Mayeur, dan Antonio Blanco. Namun, karya seni pelukis kelahiran Paris ini, dinilai memiliki pendekatan universalis yang lebih feminin dibandingkan karya para maestro lainnya.
Pameran lukisan bertajuk "Genevieve Couteau: The Orient and Beyond" di Galeri Nasional Indonesia (GNI) Jakarta, salah satu jawaban atas kemampuan Genevieve Couteau sebagai perupa perempuan, yang hingga kini tetap mendapat pengakuan di tengah dominasi perupa pria. Pameran yang digelar Institut Prancis di Indonesia (IFI) menggandeng GNI Jakarta ini, juga menjadi penting karena sebagai medium penyampai pesan mengenai humanisme.
"Tema pasca-orientalis memuncul ketika saya hendak menyelenggarakan pameran lukisan karya ibu saya. Seorang perempuan Prancis yang datang ke Timur dan melukis tentang Bali dan Laos pada akhir 1960-1970- an," tutur Jean Couteau, anak mendiang Genevieve Cou teau sekaligus penggagas pameran.
Penyelenggaraan pameran yang didahului dengan simposium pada Rabu (24/1/2018) lalu, diharapkan dapat mengajak para pencinta seni untuk mempertanyakan konstruksi sejarah seni rupa Asia, khususnya Bali. Jean Couteau sendiri merasa perlu mendapatkan jawaban mengenai perbedaan kultural antara latar belakang sang ibu dan tanah timur yang menjadi objek lukisnya.
"Muncul pertanyaan dalam diri saya. Bila karyanya diwarnai latar belakang kultural yang berbeda, apakah memang mengandung unsur dominasi? Bukankah karya justru mencerminkan universalisme dan anti nasionalisme sempit khas tahun 1960-an yang muncul di Eropa, yang ditandai dengan munculnya komunitas Hippies, The Beatles, dan lain-lain," katanya.
Pada awalnya, melukis merupakan media ekspresi favorit Genevieve Couteau, baik berupa sketsa, lukisan surealis-imajiner maupun potret hitam putih. Penguasaan dan kepekaannya atas warna datang kemudian, ketika unsur rasa yang tak terperikan itu muncul, teramu dengan kehidupan nyata yang kelak menjadi ciri khas lukisan-lukisannya.
Dalam setiap karyanya selalu ada kelindan, di mana jarak intelektual dan empati lebih diutamakan ketimbang eksplorasi bentuk. Genevieve memakai teknik seni rupa modern tanpa menjadikan modernisme sebagai fokus dan tujuan seninya. Dalam setiap garis dan tarian warna, para penikmat lukisannya dapat menemukan emosi dan tema yang terbaca jelas.
Karya-karya Genevieve Couteau termasuk dalam tradisi "peintre voyageur" atau pelukis penjelajah. Pilihan ini sekaligus menunjukkan ciri khas pengembaraan estetik sang pelukis. Kehadiran identitas "sang perempuan" juga terlihat melatarbelakangi sebagian besar lukisan atau gambarnya.
Menariknya, berbeda dengan rekan-rekannya yang sebagian besar adalah pelukis pria, fokus lukisan Genevieve bukan pada tubuh, melainkan pada wajah sang perempuan yang senantiasa terlihat memandang kekejauhan, seolah mengharapkan "dunia lain", mendambakan kesempurnaan yang tak kunjung tergapai.
Ia menghadirkannya di atas kanvas sebagai catatan perjalanan sosio-psikointuitif, atau setidaknya sebagai jelajah perburuan estetik. Ia mencari ketunggalan dalam keanekaan yang ia temukan pada tempat-tempat hunian, gerakan-gerakan dan bentuk-bentuk manusia.
Salah satu kekhasan Genevieve Couteau ialah penemuan gaya baru pada setiap seri yang ia buat. Misalnya, garis-garis memanjang pada gambar-gambarnya tentang Venezia, disusul garis pendek sarat guratan yang dipakainya untuk meng gambarkan pembongkaran di Paris saat membangun Museum Pompidou. Adapun warna, merah sayup-sayup para biksu Laos menyusul biru magis Venezia dan Bali.
Apa yang meresapi dan yang menunggalkan semua itu? Suatu dialektika antara manusia dan dunia; seperti kerap ditemukan di dunia Timur yang sedemikian ia cintai. Gayanya itu kerap disebut oleh para kritikusnya sebagai "realisme magis". Sayang, manakala reputasi Genevieve mulai memuncak pada 1980-an, ia mengidap penyakit parkinson.
Ia lalu mengalihkan perhatiannya pada kegiatan sastra. Setelah bertahun-tahun hidup didera parkinson serta penyakit menua lainnya, Genevieve akhirnya wafat pada 17 Desember 2013. Ia meninggalkan banyak karya dan jejak perburuan estetik, tentunya.
Universalisme Kafah
Lulus sebagai alumnus terbaik Sekolah Tinggi Seni Rupa Nantes pada 1951, Genevieve Couteau segera tampil sebagai pelukis terkemuka di Paris. Pada 1952, ia dianugerahi piagam bergengsi Prix Lafont Noir et Blanc (Penghargaan Lafont untuk gambar hitam putih). Ada hal penting yang layak dicatat dari Genevieve Couteau, yakni perhatian khususnya pada budaya Bali dan Laos.
Di dua tempat ini pula Genevieve menemukan laku lain dari spiritualitas Asia. Namun, ia baru menelusurinya secara mendalam pada 1975 bersama putranya Jean (penulis), yang pada waktu itu mulai mempelajari budaya Bali. Bali tahun 1970-an adalah pulau yang masih hidup dalam ritme lamban, di mana orang-orangnya masih bertelanjang kaki dalam aroma budaya agraris.
Keindahan terlihat di mana-mana tanpa kontras apa pun. Semua adalah teater, musik, alam, dan keanggunan. Memang, kala itu masyarakat Bali masih sepenuhnya menguasai memori kulturalnya. Saat itu, Genevieve tinggal di Ubud dengan menyewa sebuah rumah kecil di Jalan Bisma. Setiap hari ia menjelajah jalan dan gang di desa dengan pensil senantiasa di tangannya.
Saban hari ia dapat ditemui di rumah pelukis Padangtegal, membandingkan garisnya dengan pelukis itu. Keesokan harinya ia bisa bertukar senyum dengan para perempuan penjunjung air di Sungai Campuhan, membiarkan dirinya teresapi suasana Bali. Selama empat enam bulan, ia mengasah talenta estetiknya dengan cara berbaur, menyapa, dan mengobrol sebisanya dengan orang-orang Bali.
Apa yang disumbangkan Genevieve Couteau pada Bali dalam bidang seni rupa, yaitu suatu pandangan khas perempuan pada zamannya. Berbeda dengan beberapa pendahulunya sebelum Perang Dunia kedua (Walter Spies, Rudolf Bonnet, LeMayeur, dan Hofker), bukan tubuh yang ia gambarkan, apalagi tubuh sebagai sasaran nafsu.
Bukan pula hal-hal eksotis tanda perbedaan budaya sekaligus dominasi, bukan pula keindahan alam tanda keliyanan orang Bali, melainkan wajah-wajah perempuan Bali yang pandangannya tertuju pada "dunia jauh", baik nyata maupun imajiner. Pandangan yang tidak menyiratkan minat seksual, namun persaudaraan dan hasrat pertemuan antarmanusia, juga antara manusia dengan semesta.
"Keseluruhan karya Genevieve Couteau tentang Bali dan Laos hendaknya dipahami sebagai ajakan untuk mengekspresikan identitas-identitas etno-nasional yang liyan, sekaligus melampaui identitas tersebut di dalam universalisme bernuansa magis dan spiritual," tutur Jean Couteau.
Melihat kenyataan ini, ada saja kritikus tertentu yang dipicu oleh sejarah, melihat ambiguitas politik dalam karya-karya Genevieve Couteau, seolah-olah ragam seni nonpolitisnya bersifat orientalis dan bertujuan untuk mengelabui peminat seni tentang kekelaman kenyataan politik, baik di Laos maupun di Bali, di mana Laos saat itu tengah dicabik tentara Amerika, sedangkan Bali baru saja mengalami pembunuhan missal medio 1965-1966.
"Sudah jelas bahwa karyakarya Genevieve Couteau memperlihatkan ciri ideologi budaya. Ia menganut universalisme kafah. Bali melambangkan idamannya akan harmoni-harmoni sosial. Laos melambang upaya spiritual guna mendekatkan diri dengan Yang Tak Terhingga. Bila politik tidak hadir dalam karyanya, bukanlah karena ia tidak hadir dalam realitas, namun karena kita wajib melampauinya. Bagaimana Genevieve mencari kesamaan pada liyan, ia kerap mengatakannya kepada saya dengan kuas atau pensil di tangannya," papar Jean.
Pameran lukisan bertajuk "Genevieve Couteau: The Orient and Beyond" di Galeri Nasional Indonesia (GNI) Jakarta, salah satu jawaban atas kemampuan Genevieve Couteau sebagai perupa perempuan, yang hingga kini tetap mendapat pengakuan di tengah dominasi perupa pria. Pameran yang digelar Institut Prancis di Indonesia (IFI) menggandeng GNI Jakarta ini, juga menjadi penting karena sebagai medium penyampai pesan mengenai humanisme.
"Tema pasca-orientalis memuncul ketika saya hendak menyelenggarakan pameran lukisan karya ibu saya. Seorang perempuan Prancis yang datang ke Timur dan melukis tentang Bali dan Laos pada akhir 1960-1970- an," tutur Jean Couteau, anak mendiang Genevieve Cou teau sekaligus penggagas pameran.
Penyelenggaraan pameran yang didahului dengan simposium pada Rabu (24/1/2018) lalu, diharapkan dapat mengajak para pencinta seni untuk mempertanyakan konstruksi sejarah seni rupa Asia, khususnya Bali. Jean Couteau sendiri merasa perlu mendapatkan jawaban mengenai perbedaan kultural antara latar belakang sang ibu dan tanah timur yang menjadi objek lukisnya.
"Muncul pertanyaan dalam diri saya. Bila karyanya diwarnai latar belakang kultural yang berbeda, apakah memang mengandung unsur dominasi? Bukankah karya justru mencerminkan universalisme dan anti nasionalisme sempit khas tahun 1960-an yang muncul di Eropa, yang ditandai dengan munculnya komunitas Hippies, The Beatles, dan lain-lain," katanya.
Pada awalnya, melukis merupakan media ekspresi favorit Genevieve Couteau, baik berupa sketsa, lukisan surealis-imajiner maupun potret hitam putih. Penguasaan dan kepekaannya atas warna datang kemudian, ketika unsur rasa yang tak terperikan itu muncul, teramu dengan kehidupan nyata yang kelak menjadi ciri khas lukisan-lukisannya.
Dalam setiap karyanya selalu ada kelindan, di mana jarak intelektual dan empati lebih diutamakan ketimbang eksplorasi bentuk. Genevieve memakai teknik seni rupa modern tanpa menjadikan modernisme sebagai fokus dan tujuan seninya. Dalam setiap garis dan tarian warna, para penikmat lukisannya dapat menemukan emosi dan tema yang terbaca jelas.
Karya-karya Genevieve Couteau termasuk dalam tradisi "peintre voyageur" atau pelukis penjelajah. Pilihan ini sekaligus menunjukkan ciri khas pengembaraan estetik sang pelukis. Kehadiran identitas "sang perempuan" juga terlihat melatarbelakangi sebagian besar lukisan atau gambarnya.
Menariknya, berbeda dengan rekan-rekannya yang sebagian besar adalah pelukis pria, fokus lukisan Genevieve bukan pada tubuh, melainkan pada wajah sang perempuan yang senantiasa terlihat memandang kekejauhan, seolah mengharapkan "dunia lain", mendambakan kesempurnaan yang tak kunjung tergapai.
Ia menghadirkannya di atas kanvas sebagai catatan perjalanan sosio-psikointuitif, atau setidaknya sebagai jelajah perburuan estetik. Ia mencari ketunggalan dalam keanekaan yang ia temukan pada tempat-tempat hunian, gerakan-gerakan dan bentuk-bentuk manusia.
Salah satu kekhasan Genevieve Couteau ialah penemuan gaya baru pada setiap seri yang ia buat. Misalnya, garis-garis memanjang pada gambar-gambarnya tentang Venezia, disusul garis pendek sarat guratan yang dipakainya untuk meng gambarkan pembongkaran di Paris saat membangun Museum Pompidou. Adapun warna, merah sayup-sayup para biksu Laos menyusul biru magis Venezia dan Bali.
Apa yang meresapi dan yang menunggalkan semua itu? Suatu dialektika antara manusia dan dunia; seperti kerap ditemukan di dunia Timur yang sedemikian ia cintai. Gayanya itu kerap disebut oleh para kritikusnya sebagai "realisme magis". Sayang, manakala reputasi Genevieve mulai memuncak pada 1980-an, ia mengidap penyakit parkinson.
Ia lalu mengalihkan perhatiannya pada kegiatan sastra. Setelah bertahun-tahun hidup didera parkinson serta penyakit menua lainnya, Genevieve akhirnya wafat pada 17 Desember 2013. Ia meninggalkan banyak karya dan jejak perburuan estetik, tentunya.
Universalisme Kafah
Lulus sebagai alumnus terbaik Sekolah Tinggi Seni Rupa Nantes pada 1951, Genevieve Couteau segera tampil sebagai pelukis terkemuka di Paris. Pada 1952, ia dianugerahi piagam bergengsi Prix Lafont Noir et Blanc (Penghargaan Lafont untuk gambar hitam putih). Ada hal penting yang layak dicatat dari Genevieve Couteau, yakni perhatian khususnya pada budaya Bali dan Laos.
Di dua tempat ini pula Genevieve menemukan laku lain dari spiritualitas Asia. Namun, ia baru menelusurinya secara mendalam pada 1975 bersama putranya Jean (penulis), yang pada waktu itu mulai mempelajari budaya Bali. Bali tahun 1970-an adalah pulau yang masih hidup dalam ritme lamban, di mana orang-orangnya masih bertelanjang kaki dalam aroma budaya agraris.
Keindahan terlihat di mana-mana tanpa kontras apa pun. Semua adalah teater, musik, alam, dan keanggunan. Memang, kala itu masyarakat Bali masih sepenuhnya menguasai memori kulturalnya. Saat itu, Genevieve tinggal di Ubud dengan menyewa sebuah rumah kecil di Jalan Bisma. Setiap hari ia menjelajah jalan dan gang di desa dengan pensil senantiasa di tangannya.
Saban hari ia dapat ditemui di rumah pelukis Padangtegal, membandingkan garisnya dengan pelukis itu. Keesokan harinya ia bisa bertukar senyum dengan para perempuan penjunjung air di Sungai Campuhan, membiarkan dirinya teresapi suasana Bali. Selama empat enam bulan, ia mengasah talenta estetiknya dengan cara berbaur, menyapa, dan mengobrol sebisanya dengan orang-orang Bali.
Apa yang disumbangkan Genevieve Couteau pada Bali dalam bidang seni rupa, yaitu suatu pandangan khas perempuan pada zamannya. Berbeda dengan beberapa pendahulunya sebelum Perang Dunia kedua (Walter Spies, Rudolf Bonnet, LeMayeur, dan Hofker), bukan tubuh yang ia gambarkan, apalagi tubuh sebagai sasaran nafsu.
Bukan pula hal-hal eksotis tanda perbedaan budaya sekaligus dominasi, bukan pula keindahan alam tanda keliyanan orang Bali, melainkan wajah-wajah perempuan Bali yang pandangannya tertuju pada "dunia jauh", baik nyata maupun imajiner. Pandangan yang tidak menyiratkan minat seksual, namun persaudaraan dan hasrat pertemuan antarmanusia, juga antara manusia dengan semesta.
"Keseluruhan karya Genevieve Couteau tentang Bali dan Laos hendaknya dipahami sebagai ajakan untuk mengekspresikan identitas-identitas etno-nasional yang liyan, sekaligus melampaui identitas tersebut di dalam universalisme bernuansa magis dan spiritual," tutur Jean Couteau.
Melihat kenyataan ini, ada saja kritikus tertentu yang dipicu oleh sejarah, melihat ambiguitas politik dalam karya-karya Genevieve Couteau, seolah-olah ragam seni nonpolitisnya bersifat orientalis dan bertujuan untuk mengelabui peminat seni tentang kekelaman kenyataan politik, baik di Laos maupun di Bali, di mana Laos saat itu tengah dicabik tentara Amerika, sedangkan Bali baru saja mengalami pembunuhan missal medio 1965-1966.
"Sudah jelas bahwa karyakarya Genevieve Couteau memperlihatkan ciri ideologi budaya. Ia menganut universalisme kafah. Bali melambangkan idamannya akan harmoni-harmoni sosial. Laos melambang upaya spiritual guna mendekatkan diri dengan Yang Tak Terhingga. Bila politik tidak hadir dalam karyanya, bukanlah karena ia tidak hadir dalam realitas, namun karena kita wajib melampauinya. Bagaimana Genevieve mencari kesamaan pada liyan, ia kerap mengatakannya kepada saya dengan kuas atau pensil di tangannya," papar Jean.
(amm)