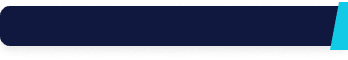Demokrasi dalam Bayang-Bayang Monarki Parpol
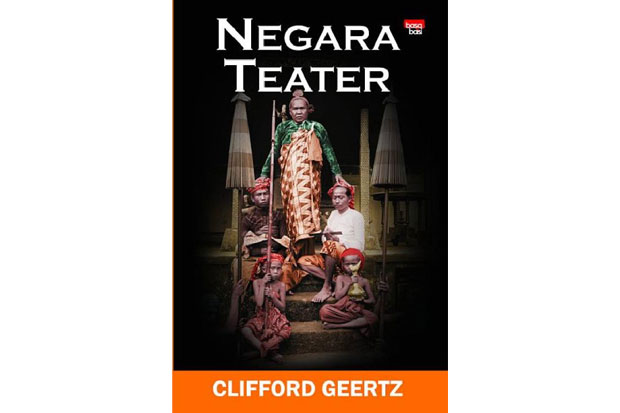
Demokrasi dalam Bayang-Bayang Monarki Parpol
A
A
A
SAAT ini, partai politik (Parpol) seperti ada dan tiada, timbul-tenggelam, datang dan pergi. Parpol ada dan hadir, sering kali hanya pada saat menjelang hajatan demokrasi, seperti pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, atau pemilihan kepala daerah.
Parpol juga hadir dalam gegap gempita kampanye politik periodik, pada momen-momen itu. Selebihnya, seperti lenyap ditelan bumi. Atau, muncul ketika ada anggotanya yang terjerat kasus korupsi. Di parlemen, parpol muncul ketika anggotanya melanggar etika atau terlibat keributan saat membahas suatu rancangan undang-undang.
Sejatinya, parpol hadir dalam segala situasi keadaan di negeri ini, bahkan berfungsi sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, sarana partisipasi politik warga negara Indonesia, dan sebagainya tidak berjalan seperti selayaknya.
Kini, partai politik selayaknya sebuah sistem monarki dalam naungan demokrasi. Situasi dalam negeri yang dulu sangat bergantung kepada kekuasaan seorang raja, kini bergantung pada kekuatan dan kekuasaan seorang ketua partai politik. Seorang ketua partai politik bisa menciptakan suasana yang kondusif dan tak kondusif. Bergantung pada kepentingan mereka masing-masing.
Beberapa partai secara terang-terangan mendirikan kerajaan dalam partai politik. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang terdekat merapat dan menjadi pengurus partai, sepertinya tidak ada pemimpin di luar pemimpin partai politik. Ironisnya, mereka menciptakan kerajaan dalam naungan sistem demokrasi; sistem yang berdaulat adalah rakyat, bukan segelintir trah tertentu saja.
Kita bukan hanya telah meninggalkan sistem monarki dan menjalankan proses demokrasi, tetapi kita juga telah menciptakan paradigma dan filosofi baru yang bernama republik-monarki. Di mana setiap orang atau kader partai politik boleh berbicara apa saja dan bebas melakukan apa saja, tetapi kalau sang ketua partai politik sudah berkata untuk diam, maka dia akan diam.
Seperti kata Geertz, raja merupakan aktor politik yang mendasarkan kekuasaan yang dia miliki melalui serangkaian upacara dan pertunjukan teatrikal. Kultus atas dirinyalah yang menaikkannya menjadi raja karena melalui drama dan teater lah gambaran kedewataan atas raja tersebut dimunculkan.
Partai politik yang menerapkan monarki, mereka melakukan ritual pencitraan semata, dan sebenarnya pemimpin yang dipilih hanya sebuah boneka demi merebut sebuah kekuasaan. Kader yang masuk partai politik tidak pernah berkotor-kotor dengan rakyat sebelumnya.
Dia masuk parpol bukan melalui suatu seleksi ketat atau prosedur standar. Dia masuk karena punya pundi-pundi finansial yang besar (pengusaha) dan popularitas (misalnya berlatar artis). Tujuannya jelas, menyokong finansial parpol dan menarik massa melalui artis yang sudah populer, jadi tidak perlu repot-repot kerja.
Rakyat saat ini juga cenderung memilih orang parpol yang sudah familier, sering wira-wiri di layar televisi sebagai bintang film, iklan, atau yang lainnya. Sang artis yang sudah populer pun tidak perlu pusing masuk parpol, tidak perlu susah belajar politik, berparlemen, atau manajemen kekuasaan.
Cukuplah popularitasnya sebagai modal utama. Lebih jauh, aksi teatrikal barangkali tidaklah membawa manfaat yang maksimal manakala raja tersebut tidak mampu mengambil loyalitas politis dari orang-orang di bawahnya. Upacara-upacara yang dilaksanakan oleh raja dengan mengerahkan setiap kemampuan yang dimilikinya boleh jadi merupakan satu mekanisme utama untuk menyerap loyalitas dari para bendoro di bawahnya.
Apa yang digambarkan oleh Geertz mengenai negara teater, dengan berbagai intrik, aliansi, pembunuhan, saling tukar perempuan, rayuan, bahkan upacara itu sendiri adalah suatu gambaran mengenai kehidupan di Bali, dan agaknya masih sangat terasa dalam konteks dunia modern.
Saya setuju sepenuhnya dengan Geertz, bahwa aksi teatrikal itu bukanlah ilusi atau dusta, bukan pula sulap atau khayalan, itu nyata sedemikian adanya. Kita tidak menghilangkan peperangan antar-kerajaan, melainkan hanya mengubah bentuknya menjadi peperangan antara partai politik.
Upeti kita sebut sebagai pajak, sumbangan, hingga sedekah. Yang berebut kekuasaan bukan lagi kerajaan-kerajaan, melainkan partai-partai politik. Partai politik telah menjadi semacam kerajaan baru di Indonesia, yang digunakan dan dijalankan dengan sistem dan kultur kerajaan. Hanya saja, demi sopan santun politik dan demokrasi kita tetap menyebutnya partai politik.
Dari buku Negara Teater kita tahu bahwa sisa-sisa negara monarki masih tersisa hingga kini. Seperti halnya di Bali, upacara (pencitraan) adalah bagian hidup masyarakat yang sudah ada secara turun-temurun dan terutama dipelihara oleh penguasa sebagai alat peraga untuk "menampakkan diri".
Makin hebat upacara yang diselenggarakan pada zaman kerajaan-kerajaan abad ke-19 itu, kian memberi kesan bahwa penguasanya besar wibawanya. Cara "menampakkan diri" si penguasa dengan menggunakan berbagai upacara tersebut, sampai kini masih bisa ditemukan di mana pun.
Ngarjito Ardi Setyanto
Ketua Garawiksa Yogyakarta
Parpol juga hadir dalam gegap gempita kampanye politik periodik, pada momen-momen itu. Selebihnya, seperti lenyap ditelan bumi. Atau, muncul ketika ada anggotanya yang terjerat kasus korupsi. Di parlemen, parpol muncul ketika anggotanya melanggar etika atau terlibat keributan saat membahas suatu rancangan undang-undang.
Sejatinya, parpol hadir dalam segala situasi keadaan di negeri ini, bahkan berfungsi sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, sarana partisipasi politik warga negara Indonesia, dan sebagainya tidak berjalan seperti selayaknya.
Kini, partai politik selayaknya sebuah sistem monarki dalam naungan demokrasi. Situasi dalam negeri yang dulu sangat bergantung kepada kekuasaan seorang raja, kini bergantung pada kekuatan dan kekuasaan seorang ketua partai politik. Seorang ketua partai politik bisa menciptakan suasana yang kondusif dan tak kondusif. Bergantung pada kepentingan mereka masing-masing.
Beberapa partai secara terang-terangan mendirikan kerajaan dalam partai politik. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang terdekat merapat dan menjadi pengurus partai, sepertinya tidak ada pemimpin di luar pemimpin partai politik. Ironisnya, mereka menciptakan kerajaan dalam naungan sistem demokrasi; sistem yang berdaulat adalah rakyat, bukan segelintir trah tertentu saja.
Kita bukan hanya telah meninggalkan sistem monarki dan menjalankan proses demokrasi, tetapi kita juga telah menciptakan paradigma dan filosofi baru yang bernama republik-monarki. Di mana setiap orang atau kader partai politik boleh berbicara apa saja dan bebas melakukan apa saja, tetapi kalau sang ketua partai politik sudah berkata untuk diam, maka dia akan diam.
Seperti kata Geertz, raja merupakan aktor politik yang mendasarkan kekuasaan yang dia miliki melalui serangkaian upacara dan pertunjukan teatrikal. Kultus atas dirinyalah yang menaikkannya menjadi raja karena melalui drama dan teater lah gambaran kedewataan atas raja tersebut dimunculkan.
Partai politik yang menerapkan monarki, mereka melakukan ritual pencitraan semata, dan sebenarnya pemimpin yang dipilih hanya sebuah boneka demi merebut sebuah kekuasaan. Kader yang masuk partai politik tidak pernah berkotor-kotor dengan rakyat sebelumnya.
Dia masuk parpol bukan melalui suatu seleksi ketat atau prosedur standar. Dia masuk karena punya pundi-pundi finansial yang besar (pengusaha) dan popularitas (misalnya berlatar artis). Tujuannya jelas, menyokong finansial parpol dan menarik massa melalui artis yang sudah populer, jadi tidak perlu repot-repot kerja.
Rakyat saat ini juga cenderung memilih orang parpol yang sudah familier, sering wira-wiri di layar televisi sebagai bintang film, iklan, atau yang lainnya. Sang artis yang sudah populer pun tidak perlu pusing masuk parpol, tidak perlu susah belajar politik, berparlemen, atau manajemen kekuasaan.
Cukuplah popularitasnya sebagai modal utama. Lebih jauh, aksi teatrikal barangkali tidaklah membawa manfaat yang maksimal manakala raja tersebut tidak mampu mengambil loyalitas politis dari orang-orang di bawahnya. Upacara-upacara yang dilaksanakan oleh raja dengan mengerahkan setiap kemampuan yang dimilikinya boleh jadi merupakan satu mekanisme utama untuk menyerap loyalitas dari para bendoro di bawahnya.
Apa yang digambarkan oleh Geertz mengenai negara teater, dengan berbagai intrik, aliansi, pembunuhan, saling tukar perempuan, rayuan, bahkan upacara itu sendiri adalah suatu gambaran mengenai kehidupan di Bali, dan agaknya masih sangat terasa dalam konteks dunia modern.
Saya setuju sepenuhnya dengan Geertz, bahwa aksi teatrikal itu bukanlah ilusi atau dusta, bukan pula sulap atau khayalan, itu nyata sedemikian adanya. Kita tidak menghilangkan peperangan antar-kerajaan, melainkan hanya mengubah bentuknya menjadi peperangan antara partai politik.
Upeti kita sebut sebagai pajak, sumbangan, hingga sedekah. Yang berebut kekuasaan bukan lagi kerajaan-kerajaan, melainkan partai-partai politik. Partai politik telah menjadi semacam kerajaan baru di Indonesia, yang digunakan dan dijalankan dengan sistem dan kultur kerajaan. Hanya saja, demi sopan santun politik dan demokrasi kita tetap menyebutnya partai politik.
Dari buku Negara Teater kita tahu bahwa sisa-sisa negara monarki masih tersisa hingga kini. Seperti halnya di Bali, upacara (pencitraan) adalah bagian hidup masyarakat yang sudah ada secara turun-temurun dan terutama dipelihara oleh penguasa sebagai alat peraga untuk "menampakkan diri".
Makin hebat upacara yang diselenggarakan pada zaman kerajaan-kerajaan abad ke-19 itu, kian memberi kesan bahwa penguasanya besar wibawanya. Cara "menampakkan diri" si penguasa dengan menggunakan berbagai upacara tersebut, sampai kini masih bisa ditemukan di mana pun.
Ngarjito Ardi Setyanto
Ketua Garawiksa Yogyakarta
(amm)