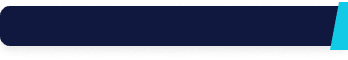Perang Gerilya Tanpa Arah

Perang Gerilya Tanpa Arah
A
A
A
Keinginan sutradara Viva Westi untuk membuat film biopik yang ringan dan tidak melelahkan patut dipuji. Namun, sang sutradara sepertinya lupa untuk membuat filmnya tak hanya ringan, juga menarik untuk ditonton.
Boleh jadi Jenderal Soedirmanadalah film bioskop pertama yang bercerita tentang perjuangan gerilya panglima besar TNI pertama tersebut. Sebuah fakta yang sebenarnya mengherankan karena Sudirman punya modal lebih dari cukup untuk dibuatkan sebuah film perang atau film biopik yang dramatis.
Sebagai panglima pertama dan termuda, dia berhasil memimpin perang gerilya selama 7 bulan dalam keadaan sakit cukup parah hingga merepotkan Belanda. Bahkan, secara tidak langsung, perang gerilya yang dijalankannya membuat Belanda bertekuk lutut dan akhirnya benar-benar mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi akhirnya, ada Viva Westi (May; Pocong Keliling; Rayya, Cahaya di Atas Cahaya) yang bertekad untuk membuat film tentang Jenderal Sudirman.
Mengaku sempat kesulitan mencari investor, akhirnya “rumah” Sudirman, yaitu Markas Besar Angkatan Darat dan beberapa yayasan/organisasi di bawahnya mau membiayai film senilai lebih dari Rp10 miliar ini. Westi dan para investor sepakat agar film dibuat ringan saja, lebih banyak adegan action daripada dialog, demi memperkenalkan sosok pahlawan hebat ini kepada penonton muda.
Sebuah ide yang cukup brilian sebenarnya karena selama ini film biopik lokal lebih sering dibuat dengan kemasan “serius” dan kurang menghibur. Namun, Westi rupanya lupa bahwa film ringan belum tentu berbanding lurus dengan film menghibur. Sepanjang menonton film ini, dibandingkan menghibur, Westi dan penulis skenario Tubagus Deddy malah lebih banyak memunculkan pertanyaan di benak penonton.
Bahkan ini sudah dimulai dengan opening scenenya yang seolah-olah dimulai dari pertengahan film. Tanpa ada satu pun petunjuk atau latar belakang tahun dan situasi untuk membimbingpenonton, tiba-tiba penonton sudah disajikan adegan pemikiran Tan Malaka (Mathias Muchus) yang radikal dan ketidaksetujuan Sudirman terhadap pikiran Tan Malaka.
Lalu, tiba-tiba lagi penonton disajikan adegan pemilihan panglima TNI yang dimenangkan oleh Sudirman. Kapan dua peristiwa tersebut terjadi? Bagaimana situasi dan kondisi politik saat peristiwa itu berlangsung? Tak ada satu pun narasi yang menjelaskan. Bahkan, bagi penonton yang mengerti sejarah, adegan pembuka ini tetap terasa ganjil.
Membiarkan penonton tanpa petunjuk terus berulang saat Sudirman memulai perang gerilyanya. Tanpa ada dialog tentang strategi menjalankan perang, rute mana dan sejauh apa jalan yang akan ditempuh pasukan (untuk memberikan gambaran kepada penonton tentang beratnya perang tersebut), tiba-tiba adegan sudah menunjukkan pasukan yang berjalan keluar masuk hutan entah mau ke mana.
Memang, film dengan cukup teliti menceritakan adegan-adegan penting nan gawat yang menimpa pasukan, misalnya saat ada anggota pasukan yang menyamar sebagai Sudirman untuk mengelabui pasukan Belanda, juga saat pasukan sudah terkepung oleh Belanda. Pun adegan-adegan “curhat” antara Soekarno dan Hatta di rumah pengasingan adalah adegan yang langka dalam sebuah film biopik.
Namun, karena tak ada pengantar cerita dan gaya storytellingyang buruk, adegan-adegan yang sebenarnya menegangkan dan dramatis tersebut lewat begitu saja tanpa memberikan efek psikologis dan emosional yang semestinya bisa dibangun. Cara bercerita yang buruk pun akhirnya merembet pada minimnya karisma Sudirman di dalam film.
Kekerasan hatinya, ketenangannya, kehebatannya berstrategi, juga kerelaannya berkorban fisik dan harta, tak tergambar kuat dalam film. Bahkan, penonton yang tak paham sejarah, bisa jadi saat menonton film ini tak akan sadar pada fakta bahwa sesungguhnya Sudirman telah memimpin pasukan selama 7 bulan,
dan menempuh jarak sejauh 1.000 km. Sungguh untuk karakter sekuat dan sehebat Jenderal Sudirman, sesungguhnya film yang bisa berakhir baik ini malah berujung menjadi mengecewakan.
Herita endriana
Boleh jadi Jenderal Soedirmanadalah film bioskop pertama yang bercerita tentang perjuangan gerilya panglima besar TNI pertama tersebut. Sebuah fakta yang sebenarnya mengherankan karena Sudirman punya modal lebih dari cukup untuk dibuatkan sebuah film perang atau film biopik yang dramatis.
Sebagai panglima pertama dan termuda, dia berhasil memimpin perang gerilya selama 7 bulan dalam keadaan sakit cukup parah hingga merepotkan Belanda. Bahkan, secara tidak langsung, perang gerilya yang dijalankannya membuat Belanda bertekuk lutut dan akhirnya benar-benar mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi akhirnya, ada Viva Westi (May; Pocong Keliling; Rayya, Cahaya di Atas Cahaya) yang bertekad untuk membuat film tentang Jenderal Sudirman.
Mengaku sempat kesulitan mencari investor, akhirnya “rumah” Sudirman, yaitu Markas Besar Angkatan Darat dan beberapa yayasan/organisasi di bawahnya mau membiayai film senilai lebih dari Rp10 miliar ini. Westi dan para investor sepakat agar film dibuat ringan saja, lebih banyak adegan action daripada dialog, demi memperkenalkan sosok pahlawan hebat ini kepada penonton muda.
Sebuah ide yang cukup brilian sebenarnya karena selama ini film biopik lokal lebih sering dibuat dengan kemasan “serius” dan kurang menghibur. Namun, Westi rupanya lupa bahwa film ringan belum tentu berbanding lurus dengan film menghibur. Sepanjang menonton film ini, dibandingkan menghibur, Westi dan penulis skenario Tubagus Deddy malah lebih banyak memunculkan pertanyaan di benak penonton.
Bahkan ini sudah dimulai dengan opening scenenya yang seolah-olah dimulai dari pertengahan film. Tanpa ada satu pun petunjuk atau latar belakang tahun dan situasi untuk membimbingpenonton, tiba-tiba penonton sudah disajikan adegan pemikiran Tan Malaka (Mathias Muchus) yang radikal dan ketidaksetujuan Sudirman terhadap pikiran Tan Malaka.
Lalu, tiba-tiba lagi penonton disajikan adegan pemilihan panglima TNI yang dimenangkan oleh Sudirman. Kapan dua peristiwa tersebut terjadi? Bagaimana situasi dan kondisi politik saat peristiwa itu berlangsung? Tak ada satu pun narasi yang menjelaskan. Bahkan, bagi penonton yang mengerti sejarah, adegan pembuka ini tetap terasa ganjil.
Membiarkan penonton tanpa petunjuk terus berulang saat Sudirman memulai perang gerilyanya. Tanpa ada dialog tentang strategi menjalankan perang, rute mana dan sejauh apa jalan yang akan ditempuh pasukan (untuk memberikan gambaran kepada penonton tentang beratnya perang tersebut), tiba-tiba adegan sudah menunjukkan pasukan yang berjalan keluar masuk hutan entah mau ke mana.
Memang, film dengan cukup teliti menceritakan adegan-adegan penting nan gawat yang menimpa pasukan, misalnya saat ada anggota pasukan yang menyamar sebagai Sudirman untuk mengelabui pasukan Belanda, juga saat pasukan sudah terkepung oleh Belanda. Pun adegan-adegan “curhat” antara Soekarno dan Hatta di rumah pengasingan adalah adegan yang langka dalam sebuah film biopik.
Namun, karena tak ada pengantar cerita dan gaya storytellingyang buruk, adegan-adegan yang sebenarnya menegangkan dan dramatis tersebut lewat begitu saja tanpa memberikan efek psikologis dan emosional yang semestinya bisa dibangun. Cara bercerita yang buruk pun akhirnya merembet pada minimnya karisma Sudirman di dalam film.
Kekerasan hatinya, ketenangannya, kehebatannya berstrategi, juga kerelaannya berkorban fisik dan harta, tak tergambar kuat dalam film. Bahkan, penonton yang tak paham sejarah, bisa jadi saat menonton film ini tak akan sadar pada fakta bahwa sesungguhnya Sudirman telah memimpin pasukan selama 7 bulan,
dan menempuh jarak sejauh 1.000 km. Sungguh untuk karakter sekuat dan sehebat Jenderal Sudirman, sesungguhnya film yang bisa berakhir baik ini malah berujung menjadi mengecewakan.
Herita endriana
(bbg)