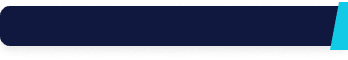Napas Ludruk, Oksigen bagi Rakyat Jelata

Napas Ludruk, Oksigen bagi Rakyat Jelata
A
A
A
JAKARTA - Piring biyen tipis-tipis, piring saiki saka porselen. Maling biyen nggawa linggis, maling saiki nggawa pulpen (Piring dahulu tipistipis, piring sekarang dari porselen.
Pencuri dahulu pakai linggis, pencuri sekarang pakai pena). Kidungan jula-juli guyon parikeno dagelan ludruk yang dibawakan Irama Budaya masih membekas di ingatan.
Mereka menjadikan ruang hiburan sebagai peringatan dan kecaman pada kondisi negeri ini yang semakin banyak koruptor dalam guyonan rakyat jelata.
Ya, seni “pemberontakan” ludruk tak lekang dalam pertarungan peradaban. Para lakonnya selalu beradaptasi, menyajikan siasat. Sama seperti pada era revolusi, ludruk menjadi sarana komunikasi antara pejuang bawah tanah dan rakyat yang menyak sikannya. Ludruk tak pernah menjadi penjilat.
Kesenian itu kini hadir dalam dinamika masyarakat yang bosan dengan perilaku menyimpang. Melalui panggung rakyat, ludruk ingin menyampaikan kegelisahan dan kebosanan rakyat kepada penguasa. Ludruk pun kembali tam pil seperti apa adanya di jalur rakyat jelata. Kehadiran seni tradisional ludruk bukan sekadar hiburan.
Di atas panggung, nasib rakyat jelata ditertawakan. Namun, mereka mengenal perlawanan dan kecintaan pada Tanah Air. Seperti kecintaan pada bangsa, kemapanan dipendarkan dan kehidupan masyarakat kecil dibumikan.
Gerakan masif dari seni modern pun tak mampu “membunuh” ludruk dengan mudah. Teknologi dengan rangkaian hiburan dan aksi pertunjukan sempat menge pung ludruk dan memojokkannya di ruang gelap kehidupan.
Sekali lagi, ludruk tetap hidup. Melalui pentas kecil-kecil di pinggiran kota, oksigen bagi rakyat jelata itu terus dialirkan. Kidungan yang khas dipertunjukan ludruk seperti menghiasi langit-langit Surabaya. Tak lelah memberikan teror sepanjang malam. Merebut mimpi-mimpi di tiap rumah, menjadikannya pertanda untuk terus waspada.
Seperti yang terlihat sore itu, seorang pria nampak keluar dari gedung pertunjukan ludruk di Jalan Kusuma Bangsa, dengan perut keroncongan. Sejak pertunjukan dimulai sam pai selesai, perutnya terus dikocok dengan kidungan jula-juli yang membuatnya terus terbahak. Malam yang bersahaja di utara Surabaya setelah hujan, sejenak berubah menjadi meriah.
Nuíman Zamroni, 46, nama pria itu, hanya membayar Rp5.000 untuk bisa menyaksikan pertunjukan ludruk. Harga yang murah di kantong nya untuk mendapatkan hiburan yang bermutu dan menyenangkan tentunya. “Masih banyak kok yang mau melihat ludruk, meskipun jumlahnya kalah dengan orang yang datang kemal-mal di Surabaya,” katanya.
Ludruk Irama Budaya salah satu yang masih bertahan di tengah gempuran. Mereka setidaknya memiliki 50 seniman ludruk yang tetap setia di jalur kebudayaan tradisional. Serangan kebudayaan baru yang menggerus ludruk membuat mereka terjepit.
Keterpurukan itu membuat mereka masih bertahan, setia di jalur kebu da ya an yang membesarkan nama Surabaya. Untuk bisa bertahan hidup, mereka masih berkutat dalam pencarian nafkah di luar jalur ludruk. Ada yang menjual koran, berdagang asongan di stasiun, juru parkir di Pasar Wonokromo, sampai tukang batu di pinggiran Surabaya.
Ketua Ludruk Irama Budaya Deden Irawan menegaskan komitmen para seniman ludruk yang masih tetap bertahan. Mata laki-laki ini terus memberikan tatapan kosong pada orang yang melintas didepan gedung pertunjukan ludruk yang ada di Taman Remaja Surabaya. Sejak pagi, dia belum merasakan sesuap nasi lewat di lambungnya.
Demikian juga dengan istri dan anak nya yang memilih untuk tiduran di kamar. Kehidupan baginya seperti peruntungan. Nasib baik terkadang datang dengan tak terduga. Namun yang pasti, tiap bulan penghasilannya dari ludruk hanya Rp40.000. Tiap tampil, ia mendapat fee Rp10.000.
“Kalau tak punya uang, itu sudah biasa. Tapi kesedihan kami akan terus terjadi kalau pertunjukan gagal dilakukan,” ujar Deden. Tiap hari Deden bersama istrinya menjalani hidup dengan apa adanya. Periuk nasi yang ada di bagian ujung kamar yang dicat warna hitam itu belum juga ada isinya.
Ruangan 3x4 meter itu menjadi singgahan baru bagi seniman ludruk Irama Budaya, setelah ber tahun-tahun bermukim di kawasan Pulo Wonokromo yang legendaris. Perjalanan mereka pun sudah dimulai di atas panggung kesenian sejak 10 November 1987. Nama Irama Budaya sendiri baru digunakan pada 1990. Sebelumnya, nama Waria Jaya disematkan.
Namun, dua tahun kemudian diganti men jadi Ikabra Jaya. Irama Budaya sendiri masuk kategori ludruk tobong. Istilah tobong diterjemahkan pentas menetap di sebuah gedung. Gedung Taman Hiburan Remaja menjadi tempat yang ke sekian kalinya mereka nobong. Pada 2010, me reka sempat nobong di Jalan Pulo Wonokromo dalam waktu yang cukup lama.
“Saat pentas di Pulo Wonokromo itulah masa kejayaan Ludruk Irama Budaya. Penonton selalu membludak, terutama jika pentas digelar pada Sabtu malam. Banyak yang ber diri dan meluber ke jalan-jalan,” katanya. Dia melanjutkan, dari kapasitas 250 kursi, yang datang bi sa lebih dari 300 orang.
Mereka rela untuk berdiri berjam-jam menunggu sampai selesai pertunjukan ludruk. “Suara ketawanya sampai nyaring,” jelasnya. Sekarang ini, kondisinya memang berbeda dari era 1990-an. Tiap selesai per tun jukan, para seniman ludruk memang menerima bayaran Rp10.000. Uang itu didapat dari karcis penonton yang di tarif Rp5.000 tiap orang.
Honor yang diterima seminggu sekali itu tentu tak cukup untuk membeli beras 1 kg. Itu pun kadang harus tekor karena biaya pertunjukan lebih besar dari pada penonton yang datang. Kalau lagi ramai, penonton yang datang bisa mencapai 200 orang.
Namun kalau lagi sepi, bisa ditonton hanya lima orang. “Berapa pun orang yang datang, kami harus tetap tampil. Makanya, banyak tekornya daripada untung,” ujarnya. (Aan Haryono)
Pencuri dahulu pakai linggis, pencuri sekarang pakai pena). Kidungan jula-juli guyon parikeno dagelan ludruk yang dibawakan Irama Budaya masih membekas di ingatan.
Mereka menjadikan ruang hiburan sebagai peringatan dan kecaman pada kondisi negeri ini yang semakin banyak koruptor dalam guyonan rakyat jelata.
Ya, seni “pemberontakan” ludruk tak lekang dalam pertarungan peradaban. Para lakonnya selalu beradaptasi, menyajikan siasat. Sama seperti pada era revolusi, ludruk menjadi sarana komunikasi antara pejuang bawah tanah dan rakyat yang menyak sikannya. Ludruk tak pernah menjadi penjilat.
Kesenian itu kini hadir dalam dinamika masyarakat yang bosan dengan perilaku menyimpang. Melalui panggung rakyat, ludruk ingin menyampaikan kegelisahan dan kebosanan rakyat kepada penguasa. Ludruk pun kembali tam pil seperti apa adanya di jalur rakyat jelata. Kehadiran seni tradisional ludruk bukan sekadar hiburan.
Di atas panggung, nasib rakyat jelata ditertawakan. Namun, mereka mengenal perlawanan dan kecintaan pada Tanah Air. Seperti kecintaan pada bangsa, kemapanan dipendarkan dan kehidupan masyarakat kecil dibumikan.
Gerakan masif dari seni modern pun tak mampu “membunuh” ludruk dengan mudah. Teknologi dengan rangkaian hiburan dan aksi pertunjukan sempat menge pung ludruk dan memojokkannya di ruang gelap kehidupan.
Sekali lagi, ludruk tetap hidup. Melalui pentas kecil-kecil di pinggiran kota, oksigen bagi rakyat jelata itu terus dialirkan. Kidungan yang khas dipertunjukan ludruk seperti menghiasi langit-langit Surabaya. Tak lelah memberikan teror sepanjang malam. Merebut mimpi-mimpi di tiap rumah, menjadikannya pertanda untuk terus waspada.
Seperti yang terlihat sore itu, seorang pria nampak keluar dari gedung pertunjukan ludruk di Jalan Kusuma Bangsa, dengan perut keroncongan. Sejak pertunjukan dimulai sam pai selesai, perutnya terus dikocok dengan kidungan jula-juli yang membuatnya terus terbahak. Malam yang bersahaja di utara Surabaya setelah hujan, sejenak berubah menjadi meriah.
Nuíman Zamroni, 46, nama pria itu, hanya membayar Rp5.000 untuk bisa menyaksikan pertunjukan ludruk. Harga yang murah di kantong nya untuk mendapatkan hiburan yang bermutu dan menyenangkan tentunya. “Masih banyak kok yang mau melihat ludruk, meskipun jumlahnya kalah dengan orang yang datang kemal-mal di Surabaya,” katanya.
Ludruk Irama Budaya salah satu yang masih bertahan di tengah gempuran. Mereka setidaknya memiliki 50 seniman ludruk yang tetap setia di jalur kebudayaan tradisional. Serangan kebudayaan baru yang menggerus ludruk membuat mereka terjepit.
Keterpurukan itu membuat mereka masih bertahan, setia di jalur kebu da ya an yang membesarkan nama Surabaya. Untuk bisa bertahan hidup, mereka masih berkutat dalam pencarian nafkah di luar jalur ludruk. Ada yang menjual koran, berdagang asongan di stasiun, juru parkir di Pasar Wonokromo, sampai tukang batu di pinggiran Surabaya.
Ketua Ludruk Irama Budaya Deden Irawan menegaskan komitmen para seniman ludruk yang masih tetap bertahan. Mata laki-laki ini terus memberikan tatapan kosong pada orang yang melintas didepan gedung pertunjukan ludruk yang ada di Taman Remaja Surabaya. Sejak pagi, dia belum merasakan sesuap nasi lewat di lambungnya.
Demikian juga dengan istri dan anak nya yang memilih untuk tiduran di kamar. Kehidupan baginya seperti peruntungan. Nasib baik terkadang datang dengan tak terduga. Namun yang pasti, tiap bulan penghasilannya dari ludruk hanya Rp40.000. Tiap tampil, ia mendapat fee Rp10.000.
“Kalau tak punya uang, itu sudah biasa. Tapi kesedihan kami akan terus terjadi kalau pertunjukan gagal dilakukan,” ujar Deden. Tiap hari Deden bersama istrinya menjalani hidup dengan apa adanya. Periuk nasi yang ada di bagian ujung kamar yang dicat warna hitam itu belum juga ada isinya.
Ruangan 3x4 meter itu menjadi singgahan baru bagi seniman ludruk Irama Budaya, setelah ber tahun-tahun bermukim di kawasan Pulo Wonokromo yang legendaris. Perjalanan mereka pun sudah dimulai di atas panggung kesenian sejak 10 November 1987. Nama Irama Budaya sendiri baru digunakan pada 1990. Sebelumnya, nama Waria Jaya disematkan.
Namun, dua tahun kemudian diganti men jadi Ikabra Jaya. Irama Budaya sendiri masuk kategori ludruk tobong. Istilah tobong diterjemahkan pentas menetap di sebuah gedung. Gedung Taman Hiburan Remaja menjadi tempat yang ke sekian kalinya mereka nobong. Pada 2010, me reka sempat nobong di Jalan Pulo Wonokromo dalam waktu yang cukup lama.
“Saat pentas di Pulo Wonokromo itulah masa kejayaan Ludruk Irama Budaya. Penonton selalu membludak, terutama jika pentas digelar pada Sabtu malam. Banyak yang ber diri dan meluber ke jalan-jalan,” katanya. Dia melanjutkan, dari kapasitas 250 kursi, yang datang bi sa lebih dari 300 orang.
Mereka rela untuk berdiri berjam-jam menunggu sampai selesai pertunjukan ludruk. “Suara ketawanya sampai nyaring,” jelasnya. Sekarang ini, kondisinya memang berbeda dari era 1990-an. Tiap selesai per tun jukan, para seniman ludruk memang menerima bayaran Rp10.000. Uang itu didapat dari karcis penonton yang di tarif Rp5.000 tiap orang.
Honor yang diterima seminggu sekali itu tentu tak cukup untuk membeli beras 1 kg. Itu pun kadang harus tekor karena biaya pertunjukan lebih besar dari pada penonton yang datang. Kalau lagi ramai, penonton yang datang bisa mencapai 200 orang.
Namun kalau lagi sepi, bisa ditonton hanya lima orang. “Berapa pun orang yang datang, kami harus tetap tampil. Makanya, banyak tekornya daripada untung,” ujarnya. (Aan Haryono)
(nfl)