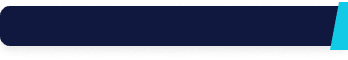Pena di Atas Langit, Habitus Kewartawanan Topan Mahdi
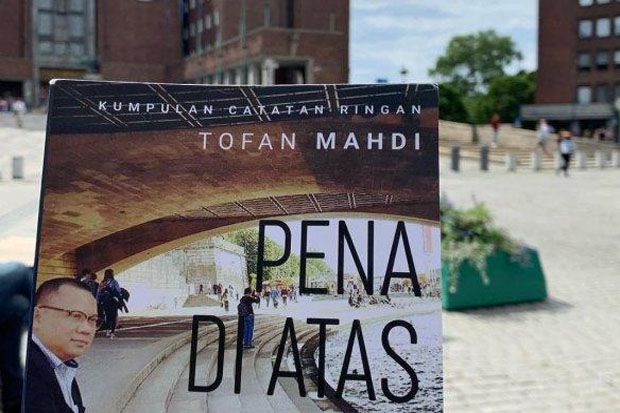
Pena di Atas Langit, Habitus Kewartawanan Topan Mahdi
A
A
A
Belum pernah saya menuntaskan baca buku hanya dalam waktu dua jam. Namun, buku berjudul Pena di Atas Langit: Kumpulan Catatan Ringan Topan Mahdi betul-betul membuat rasa penasaran berkelindan. Uniknya, setelah rampung membaca, ingin membaca ulang. Ini bukan lantaran cepatnya saya membaca sehingga masih penasaran, melainkan karena ada beberapa catatan atau tulisan yang memang butuh pemahaman, dan saya juga suka menulis.
Walau berupa bunga rampai, tapi buku ini tak ubahnya guide, bahkan bisa dikatakan modul. Bagi yang senang bepergian dan hobi menulis, terlebih yang rajin membuat catatan di dunia maya, penting sekali membaca dan mempelajari buku ini. Isi buku ini sebenarnya ringan-ringan berat, dengan tulisan sangat lugas, lentur, renyah, dan mengalir apa adanya.
Saking enak dan membuat rasa penasaran, seperti tak sabar untuk membaca halaman-halaman berikutnya. Membaca buku ini pun enjoy saja, tak mesti runut per bab atau per judul, bisa lompat-lompat dari halaman/bab belakang, depan, tengah. Suka-suka saja. Buku ini ibarat tuturan yang menjelma tulisan. Nyata sekali, si penulis buku ini begitu piawai menuangkan hasrat dan kegelisahannya.
Kelenturan menulis dengan cara berkisah bukan karena semata si penulis dulunya pernah menjadi wartawan atau sekarang aktif di praktisi kehumasan. Ini lebih karena ia begitu kukuh untuk tetap setia menulis, terus menjaga dan merawat bakat menulisnya, sekalipun sekarang dirinya menjabat vice president kehumasan di sebuah perusahaan ternama.
Anggota Dewan Pers yang juga doktor ilmu filsafat Dr Agus Sudibyo, di pengantarnya dalam buku ini mengatakan, habitus kewartawanan (Topan Mahdi) mengemuka dalam bab demi bab, halaman demi halaman dalam buku Pena di Atas Langit ini. Ekspresi, cara pandang, dan kegelisahan seorang wartawan dalam menghadapi berbagai persoalan, pun ketika yang bersangkutan secara formal tak lagi menyandang status wartawan.
Menggunakan istilah filsuf Prancis, Pierre Boudiue, kewartawanan adalah habitus: nilai-nilai sosial yang dihayati seseorang, terbentuk melalui pergulatan hidup yang panjang, lalu secara laten membentuk watak, ciri, dan perilaku orang tersebut. Habitus begitu kuat tertanam sehingga secara refleks akan mengarahkan bagaimana seseorang bersikap dan memandang permasalahan.
"Buku ini juga memberi gambaran tentang bagaimana seorang 'mantan wartawan' mesti berkiprah. Setelah tidak menjadi wartawan aktif lagi, apa yang mesti dilakukan? Sejauh mana mentalitas dan sentuhan jurnalis tetap dijaga ketika yang bersangkutan bergerak di ruang-ruang baru? Bagaimana laku jurnalistik yang bertumpu pada disiplin verifikasi, prinsip independensi, akurasi dan kehati-hatian tetap dipertahankan ketika melibatkan diri dalam perbincangan publik?"(h. xiii).
Memang, menulis harus memiliki ide. Ide menulis bisa datang dari mana saja, dari penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Ide atau gagasan tersebut harus diikat dengan segera menuliskannya atau kapan saja pada saat ada kesempatan agar gagasan yang melintas tidak menguap begitu saja. Dalam menulis kita pun pasti pernah mengalami titik jenuh dan bosan. Tidak bisa menulis apa pun, tidak ada satu kalimat pun yang bisa terangkai.
Menulis adalah ungkapan jiwa, sarana mengekspresikan diri, dan menuangkan kegelisahan. Hal inilah yang berhasil diwujudkan si penulis buku Pena di Atas Langit. Menulis seperti sudah menjadi nafas hidupnya. Itulah makanya saban waktu si penulis menyempatkan untuk menulis. Kebanyakan tulisannya dikerjakan saat tengah bepergian dan berada dalam pesawat terbang. Itulah kenapa akhirnya bukunya diberi judul Pena di Atas Langit.
Sekali lagi, buku ini sangat renyah dan enak dibaca. Rasanya seperti menikmati sensasi permen Nano-nano. Dari hal remeh-temeh, seperti tentang ongkos taksi yang main tembak, cerita tentang keluarga, soal Pilpres Amerika Serikat, perseteruan abadi Israel-Palestina, hingga soal prospek bisnis sawit, dikupas dalam buku ini. Dengan cara yang lugas tentunya.
Hal luar biasa lainnya yang membuat buku ini makin nikmat dicumbu karena ada tulisan pengantar sang begawan media Dahlan Iskan, yang tak lain guru sekaligus mantan bos dari si penulis. Makin paten sebab buku ini dipermak veteran jurnalis Djoko Pitono, dan memuat testimoni-testimoni dari sejumlah praktisi humas, wartawan, pemimpin perusahaan, hingga sahabat si penulis.
Satu kekurangan buku ini, yakni tebalnya cuma 196 halaman. Bagusnya buku ini bisa lebih tebal lagi. Karena saya yakin, masih banyak catatan yang sengaja belum diungkap si penulis, dan tentunya penting juga untuk dibukukan.
Walau berupa bunga rampai, tapi buku ini tak ubahnya guide, bahkan bisa dikatakan modul. Bagi yang senang bepergian dan hobi menulis, terlebih yang rajin membuat catatan di dunia maya, penting sekali membaca dan mempelajari buku ini. Isi buku ini sebenarnya ringan-ringan berat, dengan tulisan sangat lugas, lentur, renyah, dan mengalir apa adanya.
Saking enak dan membuat rasa penasaran, seperti tak sabar untuk membaca halaman-halaman berikutnya. Membaca buku ini pun enjoy saja, tak mesti runut per bab atau per judul, bisa lompat-lompat dari halaman/bab belakang, depan, tengah. Suka-suka saja. Buku ini ibarat tuturan yang menjelma tulisan. Nyata sekali, si penulis buku ini begitu piawai menuangkan hasrat dan kegelisahannya.
Kelenturan menulis dengan cara berkisah bukan karena semata si penulis dulunya pernah menjadi wartawan atau sekarang aktif di praktisi kehumasan. Ini lebih karena ia begitu kukuh untuk tetap setia menulis, terus menjaga dan merawat bakat menulisnya, sekalipun sekarang dirinya menjabat vice president kehumasan di sebuah perusahaan ternama.
Anggota Dewan Pers yang juga doktor ilmu filsafat Dr Agus Sudibyo, di pengantarnya dalam buku ini mengatakan, habitus kewartawanan (Topan Mahdi) mengemuka dalam bab demi bab, halaman demi halaman dalam buku Pena di Atas Langit ini. Ekspresi, cara pandang, dan kegelisahan seorang wartawan dalam menghadapi berbagai persoalan, pun ketika yang bersangkutan secara formal tak lagi menyandang status wartawan.
Menggunakan istilah filsuf Prancis, Pierre Boudiue, kewartawanan adalah habitus: nilai-nilai sosial yang dihayati seseorang, terbentuk melalui pergulatan hidup yang panjang, lalu secara laten membentuk watak, ciri, dan perilaku orang tersebut. Habitus begitu kuat tertanam sehingga secara refleks akan mengarahkan bagaimana seseorang bersikap dan memandang permasalahan.
"Buku ini juga memberi gambaran tentang bagaimana seorang 'mantan wartawan' mesti berkiprah. Setelah tidak menjadi wartawan aktif lagi, apa yang mesti dilakukan? Sejauh mana mentalitas dan sentuhan jurnalis tetap dijaga ketika yang bersangkutan bergerak di ruang-ruang baru? Bagaimana laku jurnalistik yang bertumpu pada disiplin verifikasi, prinsip independensi, akurasi dan kehati-hatian tetap dipertahankan ketika melibatkan diri dalam perbincangan publik?"(h. xiii).
Memang, menulis harus memiliki ide. Ide menulis bisa datang dari mana saja, dari penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Ide atau gagasan tersebut harus diikat dengan segera menuliskannya atau kapan saja pada saat ada kesempatan agar gagasan yang melintas tidak menguap begitu saja. Dalam menulis kita pun pasti pernah mengalami titik jenuh dan bosan. Tidak bisa menulis apa pun, tidak ada satu kalimat pun yang bisa terangkai.
Menulis adalah ungkapan jiwa, sarana mengekspresikan diri, dan menuangkan kegelisahan. Hal inilah yang berhasil diwujudkan si penulis buku Pena di Atas Langit. Menulis seperti sudah menjadi nafas hidupnya. Itulah makanya saban waktu si penulis menyempatkan untuk menulis. Kebanyakan tulisannya dikerjakan saat tengah bepergian dan berada dalam pesawat terbang. Itulah kenapa akhirnya bukunya diberi judul Pena di Atas Langit.
Sekali lagi, buku ini sangat renyah dan enak dibaca. Rasanya seperti menikmati sensasi permen Nano-nano. Dari hal remeh-temeh, seperti tentang ongkos taksi yang main tembak, cerita tentang keluarga, soal Pilpres Amerika Serikat, perseteruan abadi Israel-Palestina, hingga soal prospek bisnis sawit, dikupas dalam buku ini. Dengan cara yang lugas tentunya.
Hal luar biasa lainnya yang membuat buku ini makin nikmat dicumbu karena ada tulisan pengantar sang begawan media Dahlan Iskan, yang tak lain guru sekaligus mantan bos dari si penulis. Makin paten sebab buku ini dipermak veteran jurnalis Djoko Pitono, dan memuat testimoni-testimoni dari sejumlah praktisi humas, wartawan, pemimpin perusahaan, hingga sahabat si penulis.
Satu kekurangan buku ini, yakni tebalnya cuma 196 halaman. Bagusnya buku ini bisa lebih tebal lagi. Karena saya yakin, masih banyak catatan yang sengaja belum diungkap si penulis, dan tentunya penting juga untuk dibukukan.
(don)