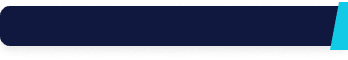Humor Humus Humilis Melankolis Kierkegaard
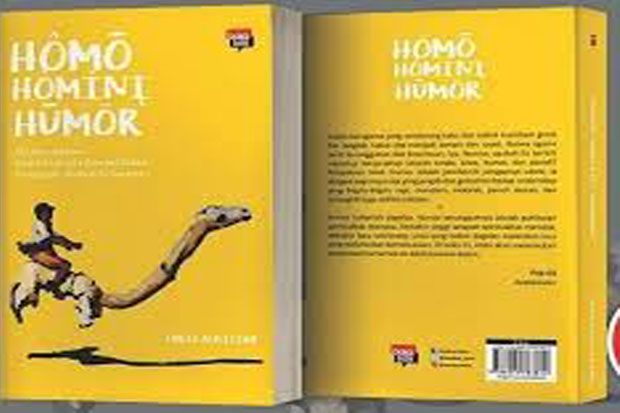
Humor Humus Humilis Melankolis Kierkegaard
A
A
A
Anton Suparyanta, product leader IPBI-MULOK di PT Penerbit Intan Pariwara Klaten-Jateng
Pumpunan 35 kelakar dalam Homo Homini Humor (2019) ini menggiring istilah homo homini socius dan homo homini lupus atau hoping ciak darling menuju kandang homo academicus kredensialis. Ada gejolak sindiran dan cibiran terhadap arti jati diri yang disandang “manusia sosial”, “manusia serigala”, dan “manusia bertopeng” untuk fokus menjadi homo ludens.
Faktanya, manusia-manusia kini gagal. Imbasnya, Fariz Alniezar memandang digdaya tiga kriteria menjadi manusia ala Soren Aabye Kierkegaard (filsuf Denmark) yang cerdik membidik ambisi-ambisi tipe manusia estetis, manusia etis, dan manusia religius.
Sebagai dosen dengan cap intelektual muda, Fariz Alniezar membutuhkan sentilan modal literasi yang dicukil-cukil dari warisan pikir Aristoteles, Umberto Eco, George Orwell, Jean Baudrillard, Harper Lee, Jean Couteau, Jan Newberry, Thomas Carlyle, Stuart Hall, Edward T Hall, Pierre Bourdieu, Ronald Dore, Rendal Collin, Ernst Cassirer, dan Desmon Morris.
Para jagoan pikir ini dijadikan dialektika untuk nutrisi keilmiahan kelakar. Barisan intelek manca ini ikut meramaikan sentilan populis gaya Gus Dur, Gus Mus, Emha Ainun Nadjib, WS Rendra, dan kaum intelek akademis Tanah Air sebagai ceruk kelakar rohani. Bahkan, mini serial kelakar Mukidi yang Banyumasan pun dicangking. Mereka berpotensi layaknya homo academicus. Setidaknya 35 kelakar dalam buku ini memasukkan nalar para intelek tersebut.
Pribadi manusia memiliki potensi untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Setiap potensi memiliki perilaku cerdas untuk berkembang. Kesalahan berperilaku mengancam setiap manusia yang berpribadi. Riak-riak ancaman inilah menjadi biang perkara yang dikemas Fariz Alniezar. Perkara yang semestinya dicap melenceng diusung menjadi kemasan humor, kelakar, dagelan, omelan, atau lelucon. Parodi dan satire menjadi ciri performa inteleknya.
Merebut Perkara
Paket perkara parodi Fariz mengingatkan paparan serius yang dilentingkan KH Mustofa Bisri tentang dua bangunan kesalehan. Ada saleh sosial, ada saleh ritual. Dengan buku ini Fariz menambahkan satu saleh, yaitu saleh jalanan.
Jadi, homo homini humor pun memantikkan tiga kesalehan pribadi manusia: saleh sosial, saleh ritual, dan saleh jalanan. Oleh karena itu, tidak salah jika perkara dalam buku ini ditegaskan dengan subtitel “kelakar agama: dari pendo(s)a sampai dinas gangguan mental beragama”.
Hebatnya, Prie GS (budayawan Semarang), mengantari buku ini dengan perkara singkat yang mengagumkan. Tandasnya, humor bukanlah dagelan. Humor sesungguhnya adalah gambaran spiritualitas manusia. Semakin tinggi tahapan spiritualitas manusia, semakin lucu seseorang. Lucu yang bukan semata-mata dagelan, melainkan lucu yang meluhurkan kemanusiaan (hlm. 3).
Mari kita rebut satu ilustrasi perkara penting keluhuran lucu yang mengatasnamakan keutamaan hidup saleh itu dengan secuwil kisah tentang pelestarian kearifan lokal. Sebab, bukankah kearifan lokal yang kini mulai luntur dari bumi nusantara ini membuat erosi setiap pribadi? Tabiat manusia gampang terpecah belah dan berujung krisis iman.
Alkisah sebagaimana cerita purba dari Pasuruan, Jawa Timur. Suatu sore si kusir delman dari Madura asyik mengantar penumpangnya mengelilingi Kota Pasuruan. Ia berkeliling dengan santai hingga tidak terasa jika delman yang dikendarainya membuat kendaraan di belakangnya antre mengular. Macet tak terkira. Kemacetan menjadi-jadi membuat seluruh antrean mobil di belakang delman melontarkan umpatan dan makian.
Hingga tatkala seorang sopir mobil di belakang delman berhasil menyalip delman. Sembari menjalankan mobilnya dengan pelan melewati delman, si sopir melantang teriak kepada si kusir, “Dasar Madura! Gara-gara kamu jalanan jadi macet.” Dengan tenang si kusir pun menyahut, “Oalah, Pak! Saya memang dari Madura, tapi kuda delman yang bikin macet ini berasal dari Jawa.” (hlm. 15)
Perkara saleh apakah yang tertanam? Ada Madura, Jawa, kusir, sopir, kuda, delman, mobil, dan kemacetan. Inikah tanda, simbol, atau ukuran untuk kesalehan agar tidak terjerumus menjadi pribadi yang berpotensi homo urakan, homo kredensialis?
Mereguk Biang
Setelah melontar pribadi-pribadi manusia beperkara, Fariz Alniezar menawarkan uji kesalehan level lebih kritis dan taktis. Bahwa puncak beragama seseorang tecermin dalam gerak-gerik perilakunya. Inilah dalam konsep filsafat disebut protopia dan bukan memamerkan utopia! Bahkan, kesuksesan keberagamaan apa pun dapat dinilai berhasil atau gagal dengan parameter seberapa beretiket, bermoral, dan berakhlakkah pribadi tersebut.
Satu tes praksis beragama menggelitik. Kita belajar agama di sekolah, di ceramah-ceramah peribadatan, dan di seminar keagamaan, maka laboratorium untuk menguji sukses tidaknya pembelajaran itu adalah jalan raya. Unik, tes kesalehan di jalan raya.
Di jalan rayalah kita bisa menilai tingkat religiositas masyarakat. Fariz menyentil. Ujian hidup sesungguhnya adalah ketika jalanan sepi. Kita berada di perempatan jalan, sedangkan lampu lalu lintas menyala merah. Keputusan untuk patuh kepada rambu-rambu lalu lintas bukan semata-mata soal keselamatan, melainkan juga perkara akhlak dan religiositas.
Sumir, nalar yang menyampah, seperti kurang kerjaan untuk cek kasus ini. Ingat, bernalarlah humor. Humor! Akan tetapi, banyak di antara kita diam-diam punya simpulan yang salah kaprah. Mulus, lebar, ya ajang kebut balap. Klakson beralih fungsi menjadi pengganggu telinga.
Awalnya sebagai tanda peringatan, kini berevolusi menjadi alat pengumpat kesal, jengkel, dan marah. Begitu kontradiktif, sarana semakin lebar dan jembar, tetapi kesadaran dan akhlak semakin ciut-menciut.
Satu kelakar cerdas dalam buku ini sebagai penutup. Segala saleh pribadi manusia pada masa kini adalah mabuk investasi saham secara material dan mabuk simbol pendidikan. Ini penyakit orang berpendidikan. Fariz Alniezar mengutip Pierre Bourdieu (1988) bahwa intelek sakit ini disebut homo academicus kredensialis.
Ronald Dore (1980) mengkritiknya dengan istilah the diploma disease, yakni penyakit sosial yang sengaja menggeser tujuan pendidikan dari butuh keilmuan dan pengetahuan menjadi sebatas demi raihan gelar akademik (hlm.102). Gawat, bukan?
Masyarakat pengidap penyakit ini berorientasi gelar mentereng sebagai modal simbolik untuk naik gengsi, raih jabatan, atau caplok kuasa. Rendal Collin (1979) mengklaim masyarakat the diploma disesase disebut masyarakat kredensial. Negara-negara berkembang menyimpan masyarakat kredensial yang menghalalkan legalitas dan formalitas sebagai supremasi tertinggi dalam kehidupan.
Fariz menyimpulkan generasi kredensial lebih mementingkan capaian, mengesampingkan proses. Pola pikirnya cupet, sumbu pendek, instan, tergesa-gesa. Akibatnya, kredensialisme melahirkan budaya palsu, imitasi, artifisial, dan membunuh kesejatian kebudayaan, bahkan menikam pribadi manusia itu sendiri.
Ujung-ujungnya yang semula sebatas wacana dalam ranah pertengkaran imajiner, kini menjadi kobar api dalam sekam. Faktanya bahwa hari-hari ini tagihan senantiasa mengalir. Bacalah, sertifikasi dan lembaganya membuncahkan kaum intelek Tanah Air.
Editor dan penulis buku mabuk, digiring arus guru, pengajar, pun karyawan yang bernafsu meraup fulus, menggegaskan diri disertifikasi secara nasional. Sertifikasi dan lembaganya kini menjadi mamon tergres di telatah negeri penuh proyek. Hipotesisnya, sertifikasi adalah proyek. Persis menjadi sebuah satire humor dalam buku anggitan Fariz Alniezar ini.
Menuai Kebusukan
Manusia besertifikat atau berijazah adalah sindrom intelek-akademis terbaru yang menyegera memasyarakat. Mereka menjadi kelas pemburu (gelar) akuan yang disahkan zaman literasi. Muncullah humor biang homo academicus kredensialis. Humor tidaklah menjadi cap negatif.
Dengan cara pandang yang berbeda, Fariz Alniezar menawarkan satire yang berbeda pula antara sikap dan semangat kerja. Inilah zaman citra yang artifisial yang mengendalikan cara pikir anak muda bekerja. Tak heran, muncullah pribadi-pribadi slilit dan mental benalu.
Kisah-kisah kelakar cerdas semacam ini membutuhkan relasionalitas tafsir antara liyan dan antiliyan. Bagaimana respons masyarakat kita? Simbol atau ukuran untuk keutamaan hidup dan kesalehan sikap justru terjerumus menjadi pribadi yang mencuatkan potensi homo urakanisme, homo kredensialis, bahkan masyarakat “ongkang-ongkang”.
Buku ini menawarkan satu konsep cerdas yang hingga kini masih menggerogoti pola pikir lintas generasi, lintas zaman, dan lintas orang-orang beriman. Segala rupa saleh pribadi manusia terkini adalah pemabuk investasi saham secara material dan pemabuk simbol pendidikan.
Status sosial getol diburu dan dijadikan sandangan supremasi pamer. Akademis cuma sebatas logosentris. Aplikasi dan praksis sengaja disingkirkan. Inilah penyakit kaum muda terpelajar, terdidik, dan berijazah. Andakah tergolong generasi homo academicus kredensialis?
Kebuntungan buku pumpunan kelakar ini terletak pada mutu esai yang tidak stabil dan persentase kurang jeli editing kata, misalnya: dimika (dinamika), baha (bahwa), tuah (tuan), membumbung (membubung), kaikinya (kakinya), komponenen (komponen), dahsayatnya (dahsyatnya), seteatretikal (seteatrikal). Selilit istilah asing, misalnya: vox pupupoli vox die (vox populi vox dei), relaity show (reality show). Banyak hipenasi masih mengganggu pembacaan. Jadi, bersungut-sungutlah membaca!
Profil buku
Judul : Homo Homini Humor
Penulis : Fariz Alniezar
Tebal : 180 halaman
Cetakan : 2019
Penerbit : Basabasi
ISBN : 978-602-5783-81-4
Pumpunan 35 kelakar dalam Homo Homini Humor (2019) ini menggiring istilah homo homini socius dan homo homini lupus atau hoping ciak darling menuju kandang homo academicus kredensialis. Ada gejolak sindiran dan cibiran terhadap arti jati diri yang disandang “manusia sosial”, “manusia serigala”, dan “manusia bertopeng” untuk fokus menjadi homo ludens.
Faktanya, manusia-manusia kini gagal. Imbasnya, Fariz Alniezar memandang digdaya tiga kriteria menjadi manusia ala Soren Aabye Kierkegaard (filsuf Denmark) yang cerdik membidik ambisi-ambisi tipe manusia estetis, manusia etis, dan manusia religius.
Sebagai dosen dengan cap intelektual muda, Fariz Alniezar membutuhkan sentilan modal literasi yang dicukil-cukil dari warisan pikir Aristoteles, Umberto Eco, George Orwell, Jean Baudrillard, Harper Lee, Jean Couteau, Jan Newberry, Thomas Carlyle, Stuart Hall, Edward T Hall, Pierre Bourdieu, Ronald Dore, Rendal Collin, Ernst Cassirer, dan Desmon Morris.
Para jagoan pikir ini dijadikan dialektika untuk nutrisi keilmiahan kelakar. Barisan intelek manca ini ikut meramaikan sentilan populis gaya Gus Dur, Gus Mus, Emha Ainun Nadjib, WS Rendra, dan kaum intelek akademis Tanah Air sebagai ceruk kelakar rohani. Bahkan, mini serial kelakar Mukidi yang Banyumasan pun dicangking. Mereka berpotensi layaknya homo academicus. Setidaknya 35 kelakar dalam buku ini memasukkan nalar para intelek tersebut.
Pribadi manusia memiliki potensi untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Setiap potensi memiliki perilaku cerdas untuk berkembang. Kesalahan berperilaku mengancam setiap manusia yang berpribadi. Riak-riak ancaman inilah menjadi biang perkara yang dikemas Fariz Alniezar. Perkara yang semestinya dicap melenceng diusung menjadi kemasan humor, kelakar, dagelan, omelan, atau lelucon. Parodi dan satire menjadi ciri performa inteleknya.
Merebut Perkara
Paket perkara parodi Fariz mengingatkan paparan serius yang dilentingkan KH Mustofa Bisri tentang dua bangunan kesalehan. Ada saleh sosial, ada saleh ritual. Dengan buku ini Fariz menambahkan satu saleh, yaitu saleh jalanan.
Jadi, homo homini humor pun memantikkan tiga kesalehan pribadi manusia: saleh sosial, saleh ritual, dan saleh jalanan. Oleh karena itu, tidak salah jika perkara dalam buku ini ditegaskan dengan subtitel “kelakar agama: dari pendo(s)a sampai dinas gangguan mental beragama”.
Hebatnya, Prie GS (budayawan Semarang), mengantari buku ini dengan perkara singkat yang mengagumkan. Tandasnya, humor bukanlah dagelan. Humor sesungguhnya adalah gambaran spiritualitas manusia. Semakin tinggi tahapan spiritualitas manusia, semakin lucu seseorang. Lucu yang bukan semata-mata dagelan, melainkan lucu yang meluhurkan kemanusiaan (hlm. 3).
Mari kita rebut satu ilustrasi perkara penting keluhuran lucu yang mengatasnamakan keutamaan hidup saleh itu dengan secuwil kisah tentang pelestarian kearifan lokal. Sebab, bukankah kearifan lokal yang kini mulai luntur dari bumi nusantara ini membuat erosi setiap pribadi? Tabiat manusia gampang terpecah belah dan berujung krisis iman.
Alkisah sebagaimana cerita purba dari Pasuruan, Jawa Timur. Suatu sore si kusir delman dari Madura asyik mengantar penumpangnya mengelilingi Kota Pasuruan. Ia berkeliling dengan santai hingga tidak terasa jika delman yang dikendarainya membuat kendaraan di belakangnya antre mengular. Macet tak terkira. Kemacetan menjadi-jadi membuat seluruh antrean mobil di belakang delman melontarkan umpatan dan makian.
Hingga tatkala seorang sopir mobil di belakang delman berhasil menyalip delman. Sembari menjalankan mobilnya dengan pelan melewati delman, si sopir melantang teriak kepada si kusir, “Dasar Madura! Gara-gara kamu jalanan jadi macet.” Dengan tenang si kusir pun menyahut, “Oalah, Pak! Saya memang dari Madura, tapi kuda delman yang bikin macet ini berasal dari Jawa.” (hlm. 15)
Perkara saleh apakah yang tertanam? Ada Madura, Jawa, kusir, sopir, kuda, delman, mobil, dan kemacetan. Inikah tanda, simbol, atau ukuran untuk kesalehan agar tidak terjerumus menjadi pribadi yang berpotensi homo urakan, homo kredensialis?
Mereguk Biang
Setelah melontar pribadi-pribadi manusia beperkara, Fariz Alniezar menawarkan uji kesalehan level lebih kritis dan taktis. Bahwa puncak beragama seseorang tecermin dalam gerak-gerik perilakunya. Inilah dalam konsep filsafat disebut protopia dan bukan memamerkan utopia! Bahkan, kesuksesan keberagamaan apa pun dapat dinilai berhasil atau gagal dengan parameter seberapa beretiket, bermoral, dan berakhlakkah pribadi tersebut.
Satu tes praksis beragama menggelitik. Kita belajar agama di sekolah, di ceramah-ceramah peribadatan, dan di seminar keagamaan, maka laboratorium untuk menguji sukses tidaknya pembelajaran itu adalah jalan raya. Unik, tes kesalehan di jalan raya.
Di jalan rayalah kita bisa menilai tingkat religiositas masyarakat. Fariz menyentil. Ujian hidup sesungguhnya adalah ketika jalanan sepi. Kita berada di perempatan jalan, sedangkan lampu lalu lintas menyala merah. Keputusan untuk patuh kepada rambu-rambu lalu lintas bukan semata-mata soal keselamatan, melainkan juga perkara akhlak dan religiositas.
Sumir, nalar yang menyampah, seperti kurang kerjaan untuk cek kasus ini. Ingat, bernalarlah humor. Humor! Akan tetapi, banyak di antara kita diam-diam punya simpulan yang salah kaprah. Mulus, lebar, ya ajang kebut balap. Klakson beralih fungsi menjadi pengganggu telinga.
Awalnya sebagai tanda peringatan, kini berevolusi menjadi alat pengumpat kesal, jengkel, dan marah. Begitu kontradiktif, sarana semakin lebar dan jembar, tetapi kesadaran dan akhlak semakin ciut-menciut.
Satu kelakar cerdas dalam buku ini sebagai penutup. Segala saleh pribadi manusia pada masa kini adalah mabuk investasi saham secara material dan mabuk simbol pendidikan. Ini penyakit orang berpendidikan. Fariz Alniezar mengutip Pierre Bourdieu (1988) bahwa intelek sakit ini disebut homo academicus kredensialis.
Ronald Dore (1980) mengkritiknya dengan istilah the diploma disease, yakni penyakit sosial yang sengaja menggeser tujuan pendidikan dari butuh keilmuan dan pengetahuan menjadi sebatas demi raihan gelar akademik (hlm.102). Gawat, bukan?
Masyarakat pengidap penyakit ini berorientasi gelar mentereng sebagai modal simbolik untuk naik gengsi, raih jabatan, atau caplok kuasa. Rendal Collin (1979) mengklaim masyarakat the diploma disesase disebut masyarakat kredensial. Negara-negara berkembang menyimpan masyarakat kredensial yang menghalalkan legalitas dan formalitas sebagai supremasi tertinggi dalam kehidupan.
Fariz menyimpulkan generasi kredensial lebih mementingkan capaian, mengesampingkan proses. Pola pikirnya cupet, sumbu pendek, instan, tergesa-gesa. Akibatnya, kredensialisme melahirkan budaya palsu, imitasi, artifisial, dan membunuh kesejatian kebudayaan, bahkan menikam pribadi manusia itu sendiri.
Ujung-ujungnya yang semula sebatas wacana dalam ranah pertengkaran imajiner, kini menjadi kobar api dalam sekam. Faktanya bahwa hari-hari ini tagihan senantiasa mengalir. Bacalah, sertifikasi dan lembaganya membuncahkan kaum intelek Tanah Air.
Editor dan penulis buku mabuk, digiring arus guru, pengajar, pun karyawan yang bernafsu meraup fulus, menggegaskan diri disertifikasi secara nasional. Sertifikasi dan lembaganya kini menjadi mamon tergres di telatah negeri penuh proyek. Hipotesisnya, sertifikasi adalah proyek. Persis menjadi sebuah satire humor dalam buku anggitan Fariz Alniezar ini.
Menuai Kebusukan
Manusia besertifikat atau berijazah adalah sindrom intelek-akademis terbaru yang menyegera memasyarakat. Mereka menjadi kelas pemburu (gelar) akuan yang disahkan zaman literasi. Muncullah humor biang homo academicus kredensialis. Humor tidaklah menjadi cap negatif.
Dengan cara pandang yang berbeda, Fariz Alniezar menawarkan satire yang berbeda pula antara sikap dan semangat kerja. Inilah zaman citra yang artifisial yang mengendalikan cara pikir anak muda bekerja. Tak heran, muncullah pribadi-pribadi slilit dan mental benalu.
Kisah-kisah kelakar cerdas semacam ini membutuhkan relasionalitas tafsir antara liyan dan antiliyan. Bagaimana respons masyarakat kita? Simbol atau ukuran untuk keutamaan hidup dan kesalehan sikap justru terjerumus menjadi pribadi yang mencuatkan potensi homo urakanisme, homo kredensialis, bahkan masyarakat “ongkang-ongkang”.
Buku ini menawarkan satu konsep cerdas yang hingga kini masih menggerogoti pola pikir lintas generasi, lintas zaman, dan lintas orang-orang beriman. Segala rupa saleh pribadi manusia terkini adalah pemabuk investasi saham secara material dan pemabuk simbol pendidikan.
Status sosial getol diburu dan dijadikan sandangan supremasi pamer. Akademis cuma sebatas logosentris. Aplikasi dan praksis sengaja disingkirkan. Inilah penyakit kaum muda terpelajar, terdidik, dan berijazah. Andakah tergolong generasi homo academicus kredensialis?
Kebuntungan buku pumpunan kelakar ini terletak pada mutu esai yang tidak stabil dan persentase kurang jeli editing kata, misalnya: dimika (dinamika), baha (bahwa), tuah (tuan), membumbung (membubung), kaikinya (kakinya), komponenen (komponen), dahsayatnya (dahsyatnya), seteatretikal (seteatrikal). Selilit istilah asing, misalnya: vox pupupoli vox die (vox populi vox dei), relaity show (reality show). Banyak hipenasi masih mengganggu pembacaan. Jadi, bersungut-sungutlah membaca!
Profil buku
Judul : Homo Homini Humor
Penulis : Fariz Alniezar
Tebal : 180 halaman
Cetakan : 2019
Penerbit : Basabasi
ISBN : 978-602-5783-81-4
(don)