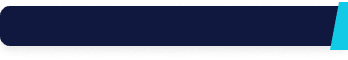Perilaku Online Remaja Berisiko Menjadi Masalah Nyata

Perilaku Online Remaja Berisiko Menjadi Masalah Nyata
A
A
A
WASHINGTON - Perilaku online remaja bisa menimbulkan masalah di kehidupan nyata seperti kekerasan dalam hubungan dan pikiran negatif mengenai citra tubuh.
Dalam dua kajian yang dipublikasikan di jurnal Pediatrics, para periset menyarankan, pendidikan dan pengawasan yang dilakukan orang tua bisa membantu mengurangi perilaku ini beserta konsekuensi negatifnya.
“Kajian itu mengonfirmasi apa yang pernah kami temukan dalam riset bahwa perilaku online akan meniru perilaku offline,” papar psikolog Jeff Temple, kepada Reuters. Temple, yang juga periset kesehatan wanita dari Texas Medical Branch di Galveston, tidak terlibat dalam dua kajian itu.
Di salah satu kajian, periset yang dipimpin Rebecca Dick di Children’s Hospital of Pittsburgh menyurvei sampel remaja berusia 14—19 tahun dari California pada tahun ajaran 2012 dan menemukan sekitar 41% melaporkan menjadi korban kekerasan kencan dunia maya selama tiga bulan pertama.
Kekerasan dalam kencan dunia maya bisa melibatkan kendali, pelecehan, ancaman dan stalking (menguntit). Kekerasan ini lebih banyak terjadi pada para gadis. Perilaku ini juga terkait risiko kekerasan fisik, kekerasan seksual dan penyerangan seksual. Menurut para periset, kekerasan kencan dunia maya juga meningkatkan risiko tidak menggunakan alat kontrasepsi dan para gadis terpaksa memiliki anak.
Dick menyatakan, riset ini adalah bagian dari kajian lebih besar yang juga akan mengamati bagaimana kekerasan kencan cyber bisa dicegah dan bagaimana menghentikan efek negatifnya. Hasilnya akan dipublikasikan pada Januari mendatang. Sampai saat itu, menurut dia, penting untuk tahu seberapa umumkah tipe kekerasan itu.
“Saya kira pesan kepada para orang tua adalah ini sangat umum dan juga bahwa kekerasan dalam hubungan—sifat tersembunyinya—bisa berbahaya bagi anak remaja mereka. Kami ingin agar para medis, pendidik kesehatan dan guru di sekolah menyadari kekerasan ini,” ujar Dick.
Dalam kajian kedua, Suzan Doornwaard di Utrecht University di Belanda dan koleganya menemukan sikap online terkait seks tidak menyebar di antara pelajar kelas 7—10 di Belanda. Itu termasuk melihat gambar-gambar porno online. Mereka yang terlibat dalam sikap itu cenderung memiliki pikiran negatif mengenai tubuh dan persepsi diri sendiri secara seksual. Penggunaan media sosial, yang lumrah di kalangan remaja, terkait lebih pada evaluasi tubuh mereka dan pengalaman seksual yang kurang memuaskan. Ini juga terkait rendahnya rasa percaya diri fisik para gadis.
“Kita mempresentasikan diri di jejaring sosial dalam pikiran yang sangat positif yang memang masuk akal. Tapi, begitu mereka melihat teman-teman mereka yang positif, mereka tidak tahan untuk membandingkan diri dengan mereka,” papar David Bickham, yang juga penulis kajian ini, dari Center on Media and Child Health di Children’s Hospital Boston.
Kajian ini juga menemukan akses yang lebih besar terhadap penggunaan internet pribadi di antara remaja dan kurangnya setelan yang dilakukan orangtua terhadap penggunaan internet terkait pada lebih banyaknya keterlibatan dalam perilaku seksual online. “Anak dan orangtua memiliki ide yang sangat berbeda mengenai kapan ada peraturan dan kapan tidak,” ujar dia.
Temple menyatakan, orang seharusnya terus memperkirakan adanya riset dan temuan seperti ini karena gadget seperti smartphone sudah umum di kalangan anak-anak dan remaja. “Kita mungkin memberikan akses anak kepada dunia online dan mengatakan ‘itu urusan mereka’ tapi saya kira kita tidak bisa melakukan itu lagi,” papar dia.
Menurut Temple, orangtua seharusnya juga hadir dalam kehidupan online anak mereka sebagaimana di kehidupan offline. Kalau itu mustahil, setidaknya orangtua memahami media sosial, termasuk Facebook, Twitter dan Instagram. “Apa yang terjadi di dunia online bisa terjadi di dunia offline dan apa yang terjadi di dunia offline bisa terjadi di dunia online,” ujar dia.
Dick menyatakan, penting juga bagi orangtua agar menunjukkan sikap online yang baik dan dalam hubungan mereka. “Penting bagi orangtua untuk memikirkan bagaimana mereka bisa menjadi model yang baik untuk anak-anaknya,” ujar Dick.
Dalam dua kajian yang dipublikasikan di jurnal Pediatrics, para periset menyarankan, pendidikan dan pengawasan yang dilakukan orang tua bisa membantu mengurangi perilaku ini beserta konsekuensi negatifnya.
“Kajian itu mengonfirmasi apa yang pernah kami temukan dalam riset bahwa perilaku online akan meniru perilaku offline,” papar psikolog Jeff Temple, kepada Reuters. Temple, yang juga periset kesehatan wanita dari Texas Medical Branch di Galveston, tidak terlibat dalam dua kajian itu.
Di salah satu kajian, periset yang dipimpin Rebecca Dick di Children’s Hospital of Pittsburgh menyurvei sampel remaja berusia 14—19 tahun dari California pada tahun ajaran 2012 dan menemukan sekitar 41% melaporkan menjadi korban kekerasan kencan dunia maya selama tiga bulan pertama.
Kekerasan dalam kencan dunia maya bisa melibatkan kendali, pelecehan, ancaman dan stalking (menguntit). Kekerasan ini lebih banyak terjadi pada para gadis. Perilaku ini juga terkait risiko kekerasan fisik, kekerasan seksual dan penyerangan seksual. Menurut para periset, kekerasan kencan dunia maya juga meningkatkan risiko tidak menggunakan alat kontrasepsi dan para gadis terpaksa memiliki anak.
Dick menyatakan, riset ini adalah bagian dari kajian lebih besar yang juga akan mengamati bagaimana kekerasan kencan cyber bisa dicegah dan bagaimana menghentikan efek negatifnya. Hasilnya akan dipublikasikan pada Januari mendatang. Sampai saat itu, menurut dia, penting untuk tahu seberapa umumkah tipe kekerasan itu.
“Saya kira pesan kepada para orang tua adalah ini sangat umum dan juga bahwa kekerasan dalam hubungan—sifat tersembunyinya—bisa berbahaya bagi anak remaja mereka. Kami ingin agar para medis, pendidik kesehatan dan guru di sekolah menyadari kekerasan ini,” ujar Dick.
Dalam kajian kedua, Suzan Doornwaard di Utrecht University di Belanda dan koleganya menemukan sikap online terkait seks tidak menyebar di antara pelajar kelas 7—10 di Belanda. Itu termasuk melihat gambar-gambar porno online. Mereka yang terlibat dalam sikap itu cenderung memiliki pikiran negatif mengenai tubuh dan persepsi diri sendiri secara seksual. Penggunaan media sosial, yang lumrah di kalangan remaja, terkait lebih pada evaluasi tubuh mereka dan pengalaman seksual yang kurang memuaskan. Ini juga terkait rendahnya rasa percaya diri fisik para gadis.
“Kita mempresentasikan diri di jejaring sosial dalam pikiran yang sangat positif yang memang masuk akal. Tapi, begitu mereka melihat teman-teman mereka yang positif, mereka tidak tahan untuk membandingkan diri dengan mereka,” papar David Bickham, yang juga penulis kajian ini, dari Center on Media and Child Health di Children’s Hospital Boston.
Kajian ini juga menemukan akses yang lebih besar terhadap penggunaan internet pribadi di antara remaja dan kurangnya setelan yang dilakukan orangtua terhadap penggunaan internet terkait pada lebih banyaknya keterlibatan dalam perilaku seksual online. “Anak dan orangtua memiliki ide yang sangat berbeda mengenai kapan ada peraturan dan kapan tidak,” ujar dia.
Temple menyatakan, orang seharusnya terus memperkirakan adanya riset dan temuan seperti ini karena gadget seperti smartphone sudah umum di kalangan anak-anak dan remaja. “Kita mungkin memberikan akses anak kepada dunia online dan mengatakan ‘itu urusan mereka’ tapi saya kira kita tidak bisa melakukan itu lagi,” papar dia.
Menurut Temple, orangtua seharusnya juga hadir dalam kehidupan online anak mereka sebagaimana di kehidupan offline. Kalau itu mustahil, setidaknya orangtua memahami media sosial, termasuk Facebook, Twitter dan Instagram. “Apa yang terjadi di dunia online bisa terjadi di dunia offline dan apa yang terjadi di dunia offline bisa terjadi di dunia online,” ujar dia.
Dick menyatakan, penting juga bagi orangtua agar menunjukkan sikap online yang baik dan dalam hubungan mereka. “Penting bagi orangtua untuk memikirkan bagaimana mereka bisa menjadi model yang baik untuk anak-anaknya,” ujar Dick.
(alv)