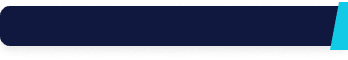Di Tengah Riuhnya Negeri

Di Tengah Riuhnya Negeri
A
A
A
Sutradara Garin Nugroho menggambarkan Tjokro sebagai pelopor pergerakan nasional, guru bagi tokoh sosialis, humanis, hingga komunis, juga Ratu Adil bagi masyarakat. Namun, Tjokro juga selalu resah dengan dirinya sendiri.
Tak banyak yang tahu sepak terjang Tjokroaminoto sebagai seorang pahlawan nasional. Padahal, tokoh ini menjadi guru bagi Sukarno, juga tokohtokoh penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Lewat Guru Bangsa , Garin berusaha menunjukkan hal tersebut. Dan, seperti yang dilakukannya pada film Soegija (2012), sutradara asal Yogyakarta ini berusaha membuat sebuah dejavu sejarah, peristiwa masa lalu yang terulang kembali pada masa sekarang.
Tumbuh pada masa kekuasaan pemerintah Belanda, Tjokro termasuk bocah yang beruntung. Dia lahir dari keluarga ningrat dan bisa mengenyam pendidikan di sekolah Belanda. Namun, terlalu sering melihat penderitaan rakyat jelata membuat Tjokro gelisah. Dia ingin berbuat sesuatu, tapi tak tahu harus berbuat apa.
Sebuah petuah agama yang disampaikan gurunya bahwa Tjokro harus berani melakukan hijrah berpindah dari kondisi yang buruk dan penuh kegelapan ke kondisi yang lebih baik sedikit membuka matanya. Hingga dewasa, kata-kata hijrah selalu menghantuinya. Puncaknya, saat istrinya, Suharsikin (Putri Ayudya), tengah hamil, kata “hijrah” tak lagi bisa dibendungnya.
Dia pamit kepada istrinya, meninggalkan keluarga, lantas pergi ke Surabaya dan memulai “karier” sebagai seorang penulis kritis di surat kabar yang didirikannya, orator ulung, hingga menjadi pemimpin Sarekat Islam (SI), sebuah organisasi besar pertama yang anggotanya mencapai 2 juta orang, mulai dari kalangan intelektual, rakyat jelata, hingga orang Arab.
Rumah Peneleh, rumah tinggal Tjokro yang juga menjadi kos-kosan, menjadi tempat bermukim Sukarno, dua tokoh pertama PKI Semaun dan Muso, serta tokoh lainnya. Di tengah kewaspadaan Belanda karena semakin besarnya pengaruh Tjokro dan SI di tengah masyarakat, anak-anak didik Tjokro justru mulai punya pandangan yang berbeda dengan dirinya.
Jalan cerita film Tjokro memang tak sesederhana sinopsis yang tertulis di sini. Ada begitu banyak yang ingin diceritakan dan dikait-kaitkan oleh Garin dan tim penulis skenario. Dari apa yang dilakukan Tjokro dengan apa yang terjadi di sekitarnya, di Belanda, bahkan di dunia.
Misalnya saat pemerintah Hindia Belanda berusaha menekan Tjokro agar Belanda bisa tenang mengeruk kekayaan Nusantara yang tengah membutuhkan banyak uang untuk perang di Eropa. Di satu sisi, Garin memang memperluas dimensi pandang penonton bahwa satu peristiwa selalu terkait dengan peristiwa lainnya. Namun, informasi yang terlalu banyak diberikan membuat film terasa riuh.
Belum lagi karakter yang juga begitu banyak, muncul sekilas-sekilas, membuat penonton terutama yang pengetahuan sejarahnya tidak banyak bisa kehilangan jejak di tengah cerita. Banyaknya kisah dan karakter yang dimunculkan berdampak pada panjangnya durasi film. Pemutaran 2,5 jam jadi terasa melelahkan karena Garin membuat ritme cerita berjalan lamban.
Dengan durasi sepanjang itu pun, karakter-karakter penting seperti Sukarno, Semaun, Muso, dan Agus Salim juga tak mendapat gambaran utuh. Tim penulis harusnya lebih “kejam” lagi untuk memilih sudut pandang mana yang ingin ditonjolkan agar cerita dan karakter-karakter dalam film bisa lebih detail digambarkan.
Meski begitu, Tjokro sesungguhnya adalah film yang sarat makna. Peristiwa yang berlangsung pada awal abad ke-20 tersebut bisa diterjemahkan Garin hingga bisa sesuai dengan kondisi sosial politik yang kini terjadi di Indonesia. Tentang kelompok ekstrem, tentang perpecahan organisasi, tentang kelompok minoritas, juga tentang keresahan seorang manusia soal hijrah diri dan bangsanya. Seperti yang ditanyakan Tjokro kepada Agus Salim, saat SI mulai redup kekuatannya. “Sudah sampai di mana hijrah kita?”
Herita endriana
Tak banyak yang tahu sepak terjang Tjokroaminoto sebagai seorang pahlawan nasional. Padahal, tokoh ini menjadi guru bagi Sukarno, juga tokohtokoh penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Lewat Guru Bangsa , Garin berusaha menunjukkan hal tersebut. Dan, seperti yang dilakukannya pada film Soegija (2012), sutradara asal Yogyakarta ini berusaha membuat sebuah dejavu sejarah, peristiwa masa lalu yang terulang kembali pada masa sekarang.
Tumbuh pada masa kekuasaan pemerintah Belanda, Tjokro termasuk bocah yang beruntung. Dia lahir dari keluarga ningrat dan bisa mengenyam pendidikan di sekolah Belanda. Namun, terlalu sering melihat penderitaan rakyat jelata membuat Tjokro gelisah. Dia ingin berbuat sesuatu, tapi tak tahu harus berbuat apa.
Sebuah petuah agama yang disampaikan gurunya bahwa Tjokro harus berani melakukan hijrah berpindah dari kondisi yang buruk dan penuh kegelapan ke kondisi yang lebih baik sedikit membuka matanya. Hingga dewasa, kata-kata hijrah selalu menghantuinya. Puncaknya, saat istrinya, Suharsikin (Putri Ayudya), tengah hamil, kata “hijrah” tak lagi bisa dibendungnya.
Dia pamit kepada istrinya, meninggalkan keluarga, lantas pergi ke Surabaya dan memulai “karier” sebagai seorang penulis kritis di surat kabar yang didirikannya, orator ulung, hingga menjadi pemimpin Sarekat Islam (SI), sebuah organisasi besar pertama yang anggotanya mencapai 2 juta orang, mulai dari kalangan intelektual, rakyat jelata, hingga orang Arab.
Rumah Peneleh, rumah tinggal Tjokro yang juga menjadi kos-kosan, menjadi tempat bermukim Sukarno, dua tokoh pertama PKI Semaun dan Muso, serta tokoh lainnya. Di tengah kewaspadaan Belanda karena semakin besarnya pengaruh Tjokro dan SI di tengah masyarakat, anak-anak didik Tjokro justru mulai punya pandangan yang berbeda dengan dirinya.
Jalan cerita film Tjokro memang tak sesederhana sinopsis yang tertulis di sini. Ada begitu banyak yang ingin diceritakan dan dikait-kaitkan oleh Garin dan tim penulis skenario. Dari apa yang dilakukan Tjokro dengan apa yang terjadi di sekitarnya, di Belanda, bahkan di dunia.
Misalnya saat pemerintah Hindia Belanda berusaha menekan Tjokro agar Belanda bisa tenang mengeruk kekayaan Nusantara yang tengah membutuhkan banyak uang untuk perang di Eropa. Di satu sisi, Garin memang memperluas dimensi pandang penonton bahwa satu peristiwa selalu terkait dengan peristiwa lainnya. Namun, informasi yang terlalu banyak diberikan membuat film terasa riuh.
Belum lagi karakter yang juga begitu banyak, muncul sekilas-sekilas, membuat penonton terutama yang pengetahuan sejarahnya tidak banyak bisa kehilangan jejak di tengah cerita. Banyaknya kisah dan karakter yang dimunculkan berdampak pada panjangnya durasi film. Pemutaran 2,5 jam jadi terasa melelahkan karena Garin membuat ritme cerita berjalan lamban.
Dengan durasi sepanjang itu pun, karakter-karakter penting seperti Sukarno, Semaun, Muso, dan Agus Salim juga tak mendapat gambaran utuh. Tim penulis harusnya lebih “kejam” lagi untuk memilih sudut pandang mana yang ingin ditonjolkan agar cerita dan karakter-karakter dalam film bisa lebih detail digambarkan.
Meski begitu, Tjokro sesungguhnya adalah film yang sarat makna. Peristiwa yang berlangsung pada awal abad ke-20 tersebut bisa diterjemahkan Garin hingga bisa sesuai dengan kondisi sosial politik yang kini terjadi di Indonesia. Tentang kelompok ekstrem, tentang perpecahan organisasi, tentang kelompok minoritas, juga tentang keresahan seorang manusia soal hijrah diri dan bangsanya. Seperti yang ditanyakan Tjokro kepada Agus Salim, saat SI mulai redup kekuatannya. “Sudah sampai di mana hijrah kita?”
Herita endriana
(bbg)