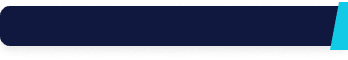Dokter Tirta Ungkap Sisi Gelap di Lingkungan Profesinya: Sengsara
loading...

Menurut Dokter Tirta, dokter merupakan profesi yang sengsara. Terlebih jika tidak menjadi dokter spesialis dan tak ditugaskan di area yang ‘strategis’. Foto/Tangkapan Layar YouTube Feni Rose Official
A
A
A
JAKARTA - Isu terkait dunia kedokteran belakangan tengah mencuat. Bahkan, sisi gelap terkait profesi ini satu per satu mulai terungkap.
Hal itu menyusul hebohnya kasus bunuh diri seorang dokter muda sekaligus peserta PPDS Anestesi Undip Semarang karena dugaan aksi perundungan. Kasus tersebut lantas membuat Dokter Tirta teringat akan sisi gelap dari profesi yang terkenal dengan ‘image’ bergaji tinggi tersebut.
Padahal, menurut Dokter Tirta, faktanya dokter merupakan sebuah profesi yang sengsara. Terlebih jika tidak menjadi dokter spesialis dan tak ditugaskan di area yang ‘strategis’.
“Justru saat itu (setelah masuk kuliah kedokteran) aku baru tahu, ternyata jadi dokter kalau nggak jadi spesialis itu sengsara. Dan kalaupun jadi spesialis, kalau nggak di lahan basah itu juga sengsara," ujar Dokter Tirta dalam podcast bersama Feni Rose, melansir dari kanal YouTube Feni Rose Official, Rabu (21/8/2024).
Dokter Tirta menyebut, proses menjadi dokter spesialis juga tidak mudah. Butuh perjuangan yang sangat keras. Mulai dari masa kuliah yang lama hingga harus dibayar murah saat pertama kali menjalani profesi.
Bahkan jika tidak memiliki ‘networking’ alias jalur ‘ordal’, Dokter Tirta menyebut, di awal-awal karier, profesi dokter akan banyak memiliki tantangan karena bisa ditugaskan di daerah yang jauh dari keluarga dan penuh dengan lingkungan tidak sehat.
“Prosesnya tuh kaya maraton. Kuliahnya lama banget dan proses juga lama. Setelah lulus dokter umum harus internship. Setelah internship gajinya pas-pasan dan harus berjuang keras lima tahun lagi untuk jadi spesialis,” ungkapnya.
“Setelah lima tahun kalau punya networking bagus akan kerja di lahan basah. Jadi lahan basah tuh deket keluarga, masih di Pulau Jawa. Tapi kalau ingin tantangan bisa ke daerah tiga T yang mana sangat stressful dan jauh dari keluarga,” lanjut dokter yang juga kreator konten itu.
Dokter lulusan Universitas Gadjah Mada itu lantas mencontohkan perjuangannya ketika menjalani koas (co-ass) pada tahun 2014, tepatnya pada saat program BPJS Kesehatan di Indonesia perdana diberlakukan. Saat itu, Dokter Tirta sempat mengira, perjuangannya telah selesai usai menjadi dokter umum.
Ia berpikir, setelah itu akan dinas di puskesmas, kemudian mengambil SIP dan lantas berekspetasi mendapat gaji sekitar Rp30-Rp40 juta. Namun, faktanya justru tidak demikian.
“Itu udah keos banget, antrean BPJS panjang. Jadi saat itu aku melihat uncertain, wah pusing banget nih. Kupikir setelah jadi dokter umum, udah. Kita dinas di puskesmas, ambil 3 SIP, atau dokter-dokter kita udah bisa dapet gaji 30-40 (juta). Ternyata nggak,” tuturnya.
Bahkan, Dokter Tirta mengaku, saat itu ia justru hanya menerima upah shift jaga sekitar Rp100-Rp150 ribu per hari. Dari sana, Dokter Tirta mulai merasa bahwa profesi dokter kerap mendapat upah yang tidak sebanding dengan perjuangan mereka.
“Uang duduk aja (saat itu) masih 100-150 ribu sehari. Uang duduk itu di dalam dokter ada yang jaga. Kalau kita jaga duduk doang itu sehari segitu,” katanya.
Namun, di sisi lain, masyarakat dan sejumlah pihak justru berdalih bahwa profesi dokter adalah sebuah pengabdian yang semestinya mereka lakukan dengan ikhlas.
“Lebih ke waktu yang harus dikorbankan, ternyata mendapatkan ganjaran uang segitu. Ketika kita komplain soal uang, masyarakat bilang, kan ini pengabdian. Tapi kan aku butuh duit untuk makan,” ungkap Dokter Tirta.
Mengetahui anggapan masyarakat yang salah tentang profesi dokter itu membuatnya miris sekaligus kesal. Pasalnya, Dokter Tirta menilai, dokter juga manusia yang butuh makan dan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
“Itu tuh hatiku yang kayak, waduh. Kita kan butuh uang buat makan ya. Kita tuh profesi kan ya. Tapi ketika kita komplain soal uang, selalu ada defence, ya kamu kan pengabdian, kalau nggak siap kenapa jadi dokter,” bebernya.
Dokter Tirta lantas menyimpulkan bahwa profesi guru dan dokter di Indonesia memang kerap dianggap harus dibayar murah. Padahal, menurutnya, yang menentukan harga layanan kesehatan murah atau mahal adalah kebijakan rumah sakit, bukan dokter.
“Bagi mereka, dipikir-pikir guru dan dokter harus dibayar murah. Yang nentuin mahal apa nggak tuh rumah sakit. Aku nggak peduli di situ,” tutupnya.
Hal itu menyusul hebohnya kasus bunuh diri seorang dokter muda sekaligus peserta PPDS Anestesi Undip Semarang karena dugaan aksi perundungan. Kasus tersebut lantas membuat Dokter Tirta teringat akan sisi gelap dari profesi yang terkenal dengan ‘image’ bergaji tinggi tersebut.
Padahal, menurut Dokter Tirta, faktanya dokter merupakan sebuah profesi yang sengsara. Terlebih jika tidak menjadi dokter spesialis dan tak ditugaskan di area yang ‘strategis’.
“Justru saat itu (setelah masuk kuliah kedokteran) aku baru tahu, ternyata jadi dokter kalau nggak jadi spesialis itu sengsara. Dan kalaupun jadi spesialis, kalau nggak di lahan basah itu juga sengsara," ujar Dokter Tirta dalam podcast bersama Feni Rose, melansir dari kanal YouTube Feni Rose Official, Rabu (21/8/2024).
Dokter Tirta menyebut, proses menjadi dokter spesialis juga tidak mudah. Butuh perjuangan yang sangat keras. Mulai dari masa kuliah yang lama hingga harus dibayar murah saat pertama kali menjalani profesi.
Bahkan jika tidak memiliki ‘networking’ alias jalur ‘ordal’, Dokter Tirta menyebut, di awal-awal karier, profesi dokter akan banyak memiliki tantangan karena bisa ditugaskan di daerah yang jauh dari keluarga dan penuh dengan lingkungan tidak sehat.
“Prosesnya tuh kaya maraton. Kuliahnya lama banget dan proses juga lama. Setelah lulus dokter umum harus internship. Setelah internship gajinya pas-pasan dan harus berjuang keras lima tahun lagi untuk jadi spesialis,” ungkapnya.
“Setelah lima tahun kalau punya networking bagus akan kerja di lahan basah. Jadi lahan basah tuh deket keluarga, masih di Pulau Jawa. Tapi kalau ingin tantangan bisa ke daerah tiga T yang mana sangat stressful dan jauh dari keluarga,” lanjut dokter yang juga kreator konten itu.
Dokter lulusan Universitas Gadjah Mada itu lantas mencontohkan perjuangannya ketika menjalani koas (co-ass) pada tahun 2014, tepatnya pada saat program BPJS Kesehatan di Indonesia perdana diberlakukan. Saat itu, Dokter Tirta sempat mengira, perjuangannya telah selesai usai menjadi dokter umum.
Ia berpikir, setelah itu akan dinas di puskesmas, kemudian mengambil SIP dan lantas berekspetasi mendapat gaji sekitar Rp30-Rp40 juta. Namun, faktanya justru tidak demikian.
“Itu udah keos banget, antrean BPJS panjang. Jadi saat itu aku melihat uncertain, wah pusing banget nih. Kupikir setelah jadi dokter umum, udah. Kita dinas di puskesmas, ambil 3 SIP, atau dokter-dokter kita udah bisa dapet gaji 30-40 (juta). Ternyata nggak,” tuturnya.
Bahkan, Dokter Tirta mengaku, saat itu ia justru hanya menerima upah shift jaga sekitar Rp100-Rp150 ribu per hari. Dari sana, Dokter Tirta mulai merasa bahwa profesi dokter kerap mendapat upah yang tidak sebanding dengan perjuangan mereka.
“Uang duduk aja (saat itu) masih 100-150 ribu sehari. Uang duduk itu di dalam dokter ada yang jaga. Kalau kita jaga duduk doang itu sehari segitu,” katanya.
Namun, di sisi lain, masyarakat dan sejumlah pihak justru berdalih bahwa profesi dokter adalah sebuah pengabdian yang semestinya mereka lakukan dengan ikhlas.
“Lebih ke waktu yang harus dikorbankan, ternyata mendapatkan ganjaran uang segitu. Ketika kita komplain soal uang, masyarakat bilang, kan ini pengabdian. Tapi kan aku butuh duit untuk makan,” ungkap Dokter Tirta.
Mengetahui anggapan masyarakat yang salah tentang profesi dokter itu membuatnya miris sekaligus kesal. Pasalnya, Dokter Tirta menilai, dokter juga manusia yang butuh makan dan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
“Itu tuh hatiku yang kayak, waduh. Kita kan butuh uang buat makan ya. Kita tuh profesi kan ya. Tapi ketika kita komplain soal uang, selalu ada defence, ya kamu kan pengabdian, kalau nggak siap kenapa jadi dokter,” bebernya.
Dokter Tirta lantas menyimpulkan bahwa profesi guru dan dokter di Indonesia memang kerap dianggap harus dibayar murah. Padahal, menurutnya, yang menentukan harga layanan kesehatan murah atau mahal adalah kebijakan rumah sakit, bukan dokter.
“Bagi mereka, dipikir-pikir guru dan dokter harus dibayar murah. Yang nentuin mahal apa nggak tuh rumah sakit. Aku nggak peduli di situ,” tutupnya.
(tsa)