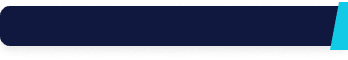Tunduk kepada Alam

Tunduk kepada Alam
A
A
A
Everest mungkin tak semenegangkan Cliffhanger atau seintens layaknya 127 Hours. Namun, film ini berhasil menunjukkan bahwa Everest adalah gunung paling berbahaya yang ada di dunia.
Film garapan Baltasar Kormakur (Contraband, 2 Guns) ini dibuat berdasarkan tragedi pendakian Everest yang terjadi pada 1996. Demi menghindari spoiler, bagi yang belum mengetahui tragedi tersebut, sebaiknya tak perlu mencari tahu terlebih dahulu sebelum menonton Everest.
Yang pasti, dibanding sebagai kisah tentang usaha menaklukkan gunung tertinggi di dunia, Everestlebih seperti film horor tentang alam yang tidak mungkin dikontrol. Everestbercerita tentang sekelompok pendaki amatir yang bermimpi menginjakkan kaki di Everest, Nepal. Begitu prestisiusnya jika berhasil mencapai puncak gunung tertinggi ini, muncullah bisnis pemandu pendakian komersial yang menampung para pendaki tersebut.
Perusahaan-perusahaan pemandu bermunculan dan para pendaki amatir harus merogoh kocek dalamdalam jika ingin dipandu oleh mereka. Akibatbisnisini, jalur pendakian ke puncak Everest jadi macet. Padahal, jalur pendakian ini tidak mudah. Adarute yang mengharuskan mereka mengantre begitu lama untuk menyeberang dari satutebing ketebinglainnya dengan menaiki tangga yang jika melihatnya akan membuat pendaki superamatir memilih pulang saja kenegara mereka.
Lama mengantre, artinya para pendaki jadi lebih banyak menghabiskan oksigen yang merekabawa. Ya, oksigen yang tipis diEverest membuat para pendaki harus menyiapkan oksigen tambahan bersama mereka. Initentu bukan sesuatu yang baik bagi para pendaki. Demi menyiasati hal tersebut, dua pemandu pendaki yang saling bersaing, Rob Hall (Jason Clarke) dan Scott Fisher (Jake Gyllenhaal) memutuskan untuk bekerja sama agar pendakian mereka lebih cepat sampai.
Kerja sama memang sangat membantu mempermudah proses pendakian, terutama saat memasang tali di Hillary Step. Ini adalah area persis sebelum puncak Everest. Lebar treknya kira-kira hanya setengah meter, tertutup salju, dengan jurang terbuka persis di samping trek. Tali dibutuhkan sebagai pengaman untuk melewati jalur tersebut.
Lepas dari Hillary Step, ada Dead Zone alias puncak Everest. Tak bisa ada yang berlama-lama di sini, karena jika ya, pasti mati. Saat para pendaki di area inilah, Everest –yang sedari awal ritmenya tergolong “santai” mulai menunjukkan wajah aslinya, sebuah film bencana yang menegangkan. Everestmulai “berulah” dan tak ada yang bisa menghentikannya.
Penonton pun harus mulai sering menahan napas, sambil harap-harap cemas, semoga semua pendaki bisa selamat. Pada saat-saat menegangkan ini pula, muncul drama yang memantik emosi penonton. Ada keluarga dan sahabat para pendaki yang menunggu mereka pulang.
Ada istri yang tengah hamil tua, istri dengan dua anak remaja, serta kolega dan sahabat di kamp kaki gunung yang menunggu suara sahabat mereka terdengar dari radio panggil. Momen-momen inilah yang membuat ketegangan berubah menjadi suasana haru. Terlebih, para tokoh dalam film ini memainkan perannya dengan sangat baik. Mereka mampu mengaduk emosi penonton.
Memang, drama dalam film ini tak dieksplorasi menjadi sebuah kekuatan bagi Everest. Namun, kelihaian film ini dalam menampilkan visualisasi gunung Everest yang begitu kokoh bersalju, dengan lingkungan sekitarnya yang juga tak kalah misteriusnya, benar-benar mampu memberi gambaran kepada para penonton tentang betapa berbahayanya gunung tersebut bagi siapa pun, bahkan bagi para pendaki profesional yang sudah bolak-balik menginjakkan kaki di puncak Everest.
Juga bagi para pendaki dan pemandu lokal yang disebut Sherpa. Lokasi syuting yang mengambil tempat di Everest hingga di kamp 2, juga di wilayah pegunungan Otztal Alps di Italia dan di Islandia, sangat membantu mewujudkan visualisasi Everest yang mendekati aslinya. Boleh dibilang, hanya dengan bermodal penampakan Everest pun, tanpa skenario yang apik atau adeganadegan ketegangan yang intens, Everest sudah bisa memukau penonton.
Herita endriana
Film garapan Baltasar Kormakur (Contraband, 2 Guns) ini dibuat berdasarkan tragedi pendakian Everest yang terjadi pada 1996. Demi menghindari spoiler, bagi yang belum mengetahui tragedi tersebut, sebaiknya tak perlu mencari tahu terlebih dahulu sebelum menonton Everest.
Yang pasti, dibanding sebagai kisah tentang usaha menaklukkan gunung tertinggi di dunia, Everestlebih seperti film horor tentang alam yang tidak mungkin dikontrol. Everestbercerita tentang sekelompok pendaki amatir yang bermimpi menginjakkan kaki di Everest, Nepal. Begitu prestisiusnya jika berhasil mencapai puncak gunung tertinggi ini, muncullah bisnis pemandu pendakian komersial yang menampung para pendaki tersebut.
Perusahaan-perusahaan pemandu bermunculan dan para pendaki amatir harus merogoh kocek dalamdalam jika ingin dipandu oleh mereka. Akibatbisnisini, jalur pendakian ke puncak Everest jadi macet. Padahal, jalur pendakian ini tidak mudah. Adarute yang mengharuskan mereka mengantre begitu lama untuk menyeberang dari satutebing ketebinglainnya dengan menaiki tangga yang jika melihatnya akan membuat pendaki superamatir memilih pulang saja kenegara mereka.
Lama mengantre, artinya para pendaki jadi lebih banyak menghabiskan oksigen yang merekabawa. Ya, oksigen yang tipis diEverest membuat para pendaki harus menyiapkan oksigen tambahan bersama mereka. Initentu bukan sesuatu yang baik bagi para pendaki. Demi menyiasati hal tersebut, dua pemandu pendaki yang saling bersaing, Rob Hall (Jason Clarke) dan Scott Fisher (Jake Gyllenhaal) memutuskan untuk bekerja sama agar pendakian mereka lebih cepat sampai.
Kerja sama memang sangat membantu mempermudah proses pendakian, terutama saat memasang tali di Hillary Step. Ini adalah area persis sebelum puncak Everest. Lebar treknya kira-kira hanya setengah meter, tertutup salju, dengan jurang terbuka persis di samping trek. Tali dibutuhkan sebagai pengaman untuk melewati jalur tersebut.
Lepas dari Hillary Step, ada Dead Zone alias puncak Everest. Tak bisa ada yang berlama-lama di sini, karena jika ya, pasti mati. Saat para pendaki di area inilah, Everest –yang sedari awal ritmenya tergolong “santai” mulai menunjukkan wajah aslinya, sebuah film bencana yang menegangkan. Everestmulai “berulah” dan tak ada yang bisa menghentikannya.
Penonton pun harus mulai sering menahan napas, sambil harap-harap cemas, semoga semua pendaki bisa selamat. Pada saat-saat menegangkan ini pula, muncul drama yang memantik emosi penonton. Ada keluarga dan sahabat para pendaki yang menunggu mereka pulang.
Ada istri yang tengah hamil tua, istri dengan dua anak remaja, serta kolega dan sahabat di kamp kaki gunung yang menunggu suara sahabat mereka terdengar dari radio panggil. Momen-momen inilah yang membuat ketegangan berubah menjadi suasana haru. Terlebih, para tokoh dalam film ini memainkan perannya dengan sangat baik. Mereka mampu mengaduk emosi penonton.
Memang, drama dalam film ini tak dieksplorasi menjadi sebuah kekuatan bagi Everest. Namun, kelihaian film ini dalam menampilkan visualisasi gunung Everest yang begitu kokoh bersalju, dengan lingkungan sekitarnya yang juga tak kalah misteriusnya, benar-benar mampu memberi gambaran kepada para penonton tentang betapa berbahayanya gunung tersebut bagi siapa pun, bahkan bagi para pendaki profesional yang sudah bolak-balik menginjakkan kaki di puncak Everest.
Juga bagi para pendaki dan pemandu lokal yang disebut Sherpa. Lokasi syuting yang mengambil tempat di Everest hingga di kamp 2, juga di wilayah pegunungan Otztal Alps di Italia dan di Islandia, sangat membantu mewujudkan visualisasi Everest yang mendekati aslinya. Boleh dibilang, hanya dengan bermodal penampakan Everest pun, tanpa skenario yang apik atau adeganadegan ketegangan yang intens, Everest sudah bisa memukau penonton.
Herita endriana
(ftr)