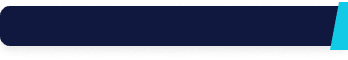Kho Ping Hoo, Suling Emas Jilid 15 Bagian 10
loading...
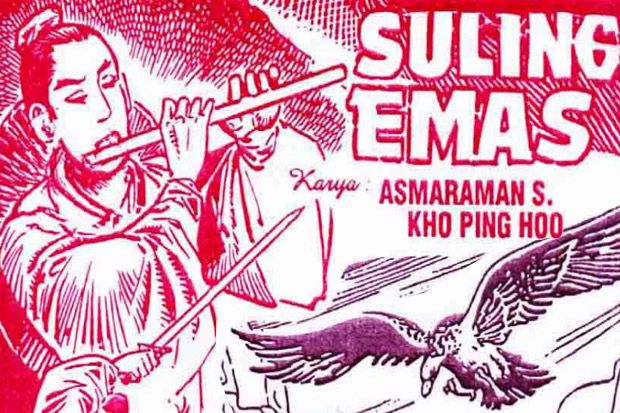
Suling Emas, karya : Asmaraman S Kho Ping Hoo
A
A
A
Kho Ping Hoo, Suling Emas
Karena semenjak kecil ia memang hidup sebagai putera seorang pembesar yang serba cukup, maka biarpun sekarang telah menjadi seorang "gelandangan", namun Bu Song selalu dapat menjaga dirinya agar tetap bersih dan sehat, biarpun pakaiannya kemudian habis dijualnya untuk makan sehingga yang dimilikinya hanya yang menempel pada tubuhnya, namun ia merawat pakaian itu dengan hati-hati, mencucinya setiap kali pakaian itu kotor. Oleh karena inilah, Bu Song selalu tampak sehat dan bersih, tidak seperti seorang anak jembel.
Pada suatu hari dalam perantauannya tanpa arah, tibalah Bu Song di lembah Sungai Huai yang subur daerahnya. Ia meninggalkan Kabupaten Jwee-bun dimana ia tinggal selama sebulan dan bekerja membantu seorang pemilik rumah makan. Kini, dengan bekal sisa uang gajinya, Bu Song berangkat pagi-pagi meninggalkan Jwee-bun, terus ke timur melalui hutan-hutan kecil sepanjang lembah sungai.
Matahari sudah naik tinggi, sinarnya menerobos celah-celah daun pohon di atas kepalanya. Angin semilir berdendang dengan daun bunga, mengiringi nyanyian burung-burung hutan. Di sana-sini, binatang kelinci dengan telinganya yang panjang-panjang berlompatan saling kejar dan bermain "sembunyi-cari" dengan teman-temannya di antara rumpun. Demikian indah pemandangan, demikian merdu pendengaran, demikian nyaman perasaan pada pagi cerah itu sehingga Bu Song lupa akan segala kesukaran yang pernah ia alami maupun yang akan ia hadapi. Anak ini berdiri diam tak bergerak agar jangan mengagetkan kelinci-kelinci itu, menonton mereka bermain-main dengan hati geli.
"Ha-ha-ha! Akulah raja di antara segala raja! Dikawal monyet-monyet berkuda! Ha-ha-ha!"
Bu Song tersentak kaget mendengar tiba-tiba ada suara ketawa yang disambung kata-kata yang dinyanyikan itu. Suara itu datangnya dari belakang, masih jauh sekali. Heran sekali ia, mengapa di dalam hutan sesunyi ini ada seorang bernyanyi seaneh itu. Orang gilakah? Akan tetapi ia menjadi makin heran ketika mendengar suaran kaki kuda, kemudian melihat munculnya lima ekor kuda besar-besar ditunggangi lima orang yang wajahnya kelihatan bengis-bengis.
Kuda terdepan yang ditunggangi oleh seorang laki-laki tinggi besar bermuka hitam, menyeret seorang laki-laki yang rambutnya compang-camping penuh tambalan. Laki-laki aneh inilah yang agaknya bernyanyi tadi, karena memang keadaannya seperti orang gila. Kedua lengannya terikat dengan tali yang cukup besar dan kuat, dan ujung tali ikatan ini dipegang oleh Si Penunggang Kuda.
Si gila ini tangan kanannya memegang sebuah paha panggang yang besar, mungkin paha angsa atau kalkun, yang digerogotinya. Biarpun kedua lengannya terikat, ia kelihatan enak-enak saja, diseret kuda ia malah menari dan bernyanyi-nyanyi, sama sekali tidak kelihatan takut. Terang dia gila, pikir Bu Song. Ia memperhatikan lima orang itu. Mereka kelihatan galak dan membawa senjata tajam. Rasa iba menyesak di dadanya. Orang itu jelas gila, berarti dalam sakit. Kenapa harus disiksa seperti itu?
Tentu saja Bu Song tidak tahu bahwa yang ia sangka gila itu adalah seorang sakti yang telah menggemparkan dunia kang-ouw dengan perbuatannya yang hebat dalam menentang kejahatan, disertai tindakannya yang selalu edan-edanan seperti orang tidak waras otaknya. Dan agaknya sangat boleh jadi lima orang itu juga seperti Bu Song, tidak tahu sama sekali bahwa yang mereka tangkap itu adalah Kim-mo Taisu, pendekar sastrawan gila yang dahulu adalah seorang sastrawan tampan dan gagah bernama Kwee Seng dan berjuluk Kim-mo eng!
Terdorong oleh rasa kasihan, Bu Song berlari menghampiri orang gila itu. "He, bocah! Mau apa kau??" Seorang di antara para penunggang kuda itu membentak, tangannya bergerak dan cambuk di tangannya itu mengeluarkan bunyi "tar-tar-tar" seperti mercon.
"Aku hanya ingin bicara dengan Paman, apa salahnya?" Bu Song menjawab dan ia nekat mendekati terus biarpun ia diancam dengan cambuk yang panjang dan dapat berbunyi menakutkan itu.
Laki-laki gila itu dengan enaknya menggigit sepotong daging dari paha panggang yang dipegangnya, lau melirik ke kanan memandang Bu Song, tertawa dan berkata. "Eh, bocah sinting! Kau lapar? Nih, kau boleh gigit dan makan sepotong!" Sedapatnya ia mengelurkan tangannya yang terikat untuk memberikan paha panggang itu kepada Bu Song.
"Tidak, Paman, aku tidak lapar. Kau makanlah sendiri." Bu Song terpaksa harus maju setengah berlari untuk mengimbangi orang gila yang terseret di belakang kuda itu. Orang gila itu terpaksa pula melangkah lebar dan terhuyung-huyung. "Paman, kenapa kau ditawan? Apakah kesalahanmu? Dan kau hendak dibawa ke mana?"
"Bocah gila! Pergi kau! Tar-tar-tar!" Cambuk di tangan penunggang kuda yang paling belakang, melecut ke arah Bu Song dan orang gila itu. Cambuk itu panjang dan tangan yang memegangnya biarpun kurus namun bertenaga sehingga lecutan itu keras sekali, tepat mengenai pundak Bu Song dan leher orang gila. Akan tetapi anehnya, Bu Song sama sekali tidak merasa sakit karena ujung cambuk itu ketika mengenai tubuhnya, terpental kembali seakan-akan tertangkis tenaga yang tak tampak. (Bersambung)
Karena semenjak kecil ia memang hidup sebagai putera seorang pembesar yang serba cukup, maka biarpun sekarang telah menjadi seorang "gelandangan", namun Bu Song selalu dapat menjaga dirinya agar tetap bersih dan sehat, biarpun pakaiannya kemudian habis dijualnya untuk makan sehingga yang dimilikinya hanya yang menempel pada tubuhnya, namun ia merawat pakaian itu dengan hati-hati, mencucinya setiap kali pakaian itu kotor. Oleh karena inilah, Bu Song selalu tampak sehat dan bersih, tidak seperti seorang anak jembel.
Pada suatu hari dalam perantauannya tanpa arah, tibalah Bu Song di lembah Sungai Huai yang subur daerahnya. Ia meninggalkan Kabupaten Jwee-bun dimana ia tinggal selama sebulan dan bekerja membantu seorang pemilik rumah makan. Kini, dengan bekal sisa uang gajinya, Bu Song berangkat pagi-pagi meninggalkan Jwee-bun, terus ke timur melalui hutan-hutan kecil sepanjang lembah sungai.
Matahari sudah naik tinggi, sinarnya menerobos celah-celah daun pohon di atas kepalanya. Angin semilir berdendang dengan daun bunga, mengiringi nyanyian burung-burung hutan. Di sana-sini, binatang kelinci dengan telinganya yang panjang-panjang berlompatan saling kejar dan bermain "sembunyi-cari" dengan teman-temannya di antara rumpun. Demikian indah pemandangan, demikian merdu pendengaran, demikian nyaman perasaan pada pagi cerah itu sehingga Bu Song lupa akan segala kesukaran yang pernah ia alami maupun yang akan ia hadapi. Anak ini berdiri diam tak bergerak agar jangan mengagetkan kelinci-kelinci itu, menonton mereka bermain-main dengan hati geli.
"Ha-ha-ha! Akulah raja di antara segala raja! Dikawal monyet-monyet berkuda! Ha-ha-ha!"
Bu Song tersentak kaget mendengar tiba-tiba ada suara ketawa yang disambung kata-kata yang dinyanyikan itu. Suara itu datangnya dari belakang, masih jauh sekali. Heran sekali ia, mengapa di dalam hutan sesunyi ini ada seorang bernyanyi seaneh itu. Orang gilakah? Akan tetapi ia menjadi makin heran ketika mendengar suaran kaki kuda, kemudian melihat munculnya lima ekor kuda besar-besar ditunggangi lima orang yang wajahnya kelihatan bengis-bengis.
Kuda terdepan yang ditunggangi oleh seorang laki-laki tinggi besar bermuka hitam, menyeret seorang laki-laki yang rambutnya compang-camping penuh tambalan. Laki-laki aneh inilah yang agaknya bernyanyi tadi, karena memang keadaannya seperti orang gila. Kedua lengannya terikat dengan tali yang cukup besar dan kuat, dan ujung tali ikatan ini dipegang oleh Si Penunggang Kuda.
Si gila ini tangan kanannya memegang sebuah paha panggang yang besar, mungkin paha angsa atau kalkun, yang digerogotinya. Biarpun kedua lengannya terikat, ia kelihatan enak-enak saja, diseret kuda ia malah menari dan bernyanyi-nyanyi, sama sekali tidak kelihatan takut. Terang dia gila, pikir Bu Song. Ia memperhatikan lima orang itu. Mereka kelihatan galak dan membawa senjata tajam. Rasa iba menyesak di dadanya. Orang itu jelas gila, berarti dalam sakit. Kenapa harus disiksa seperti itu?
Tentu saja Bu Song tidak tahu bahwa yang ia sangka gila itu adalah seorang sakti yang telah menggemparkan dunia kang-ouw dengan perbuatannya yang hebat dalam menentang kejahatan, disertai tindakannya yang selalu edan-edanan seperti orang tidak waras otaknya. Dan agaknya sangat boleh jadi lima orang itu juga seperti Bu Song, tidak tahu sama sekali bahwa yang mereka tangkap itu adalah Kim-mo Taisu, pendekar sastrawan gila yang dahulu adalah seorang sastrawan tampan dan gagah bernama Kwee Seng dan berjuluk Kim-mo eng!
Terdorong oleh rasa kasihan, Bu Song berlari menghampiri orang gila itu. "He, bocah! Mau apa kau??" Seorang di antara para penunggang kuda itu membentak, tangannya bergerak dan cambuk di tangannya itu mengeluarkan bunyi "tar-tar-tar" seperti mercon.
"Aku hanya ingin bicara dengan Paman, apa salahnya?" Bu Song menjawab dan ia nekat mendekati terus biarpun ia diancam dengan cambuk yang panjang dan dapat berbunyi menakutkan itu.
Laki-laki gila itu dengan enaknya menggigit sepotong daging dari paha panggang yang dipegangnya, lau melirik ke kanan memandang Bu Song, tertawa dan berkata. "Eh, bocah sinting! Kau lapar? Nih, kau boleh gigit dan makan sepotong!" Sedapatnya ia mengelurkan tangannya yang terikat untuk memberikan paha panggang itu kepada Bu Song.
"Tidak, Paman, aku tidak lapar. Kau makanlah sendiri." Bu Song terpaksa harus maju setengah berlari untuk mengimbangi orang gila yang terseret di belakang kuda itu. Orang gila itu terpaksa pula melangkah lebar dan terhuyung-huyung. "Paman, kenapa kau ditawan? Apakah kesalahanmu? Dan kau hendak dibawa ke mana?"
"Bocah gila! Pergi kau! Tar-tar-tar!" Cambuk di tangan penunggang kuda yang paling belakang, melecut ke arah Bu Song dan orang gila itu. Cambuk itu panjang dan tangan yang memegangnya biarpun kurus namun bertenaga sehingga lecutan itu keras sekali, tepat mengenai pundak Bu Song dan leher orang gila. Akan tetapi anehnya, Bu Song sama sekali tidak merasa sakit karena ujung cambuk itu ketika mengenai tubuhnya, terpental kembali seakan-akan tertangkis tenaga yang tak tampak. (Bersambung)
(dwi)